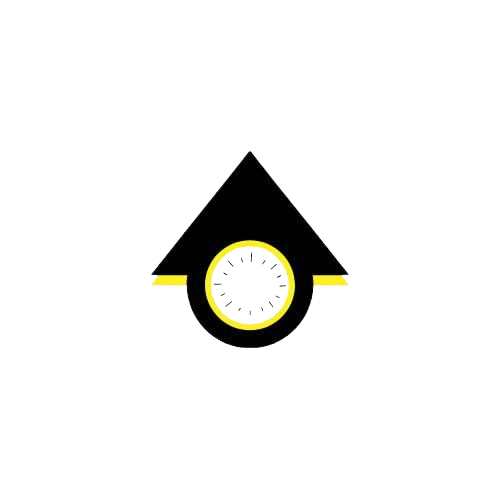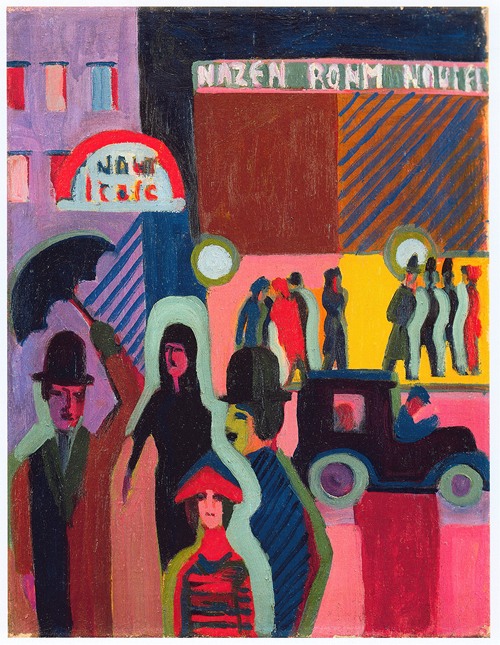foto: moch aldy ma
Pada dasarnya struktur kerja puisi menawarkan pendekatan linguistik yang unik, selain fenomenologi makna yang ada di dalam kandungnya. Atau katakanlah, kerja puisi selalu melampaui kebakuan aturan-aturan bahasa yang biasanya dipakai sehari-hari, lalu memungkinkan kebebasan dan konfigurasi ulang tentang apa-apa yang sudah mapan. Jika dikait-hubungkan secara sepintas, mungkin senada dengan sifat filsafat yang menggebrak keklisean untuk menawarkan kebaruan. Keduanya juga menggunakan bahasa sebagai alat kerjanya melalui wahana berpikir, merasa, merepresentasikan, dan lain sebagainya tentang segala bentuk yang diolah-edarkan ilmu dan pengetahuan.
Perbedaan paling mencolok dari keduanya, barangkali, terletak pada kerja puisi yang cenderung memakai ritme dan rima demi memaksimalkan pengalaman puitik serta kekayaan akan potensi bahasa. Sedangkan kerja filsafat lebih luwes dari struktur-kerangka prosesi wahana kerjanya, namun sedikit rariweuh untuk seorang awam dalam hal penyampaian olahan berpikir, memandang, memaknai, dan seterusnya. Tapi bagaimana jika kedua wahana kerja tersebut, puisi dan filsafat dikawinkan dan menyatu dari proses kreatif seseorang?
Ya, tidak gimana-gimana sih sebenarnya. Namun, begitulah kami memandang olahan kreatif berpikir dalam puisi-puisi Moch Aldy MA — alias Mochammad Aldy Maulana Adha — atawa Genrifinaldy (nama dunia mayanya). Seorang lelaki kelahiran 27 Maret 2000 di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecintaannya pada dunia filsuf dan penyair, menghasilkan pengalaman berpikir melalui sastra di dalam hidupnya, khususnya puisi yang menarik sekaligus sering mengusik pikiran pembaca.
Menyangkut karya-karyanya, pembaca dapat menelusuri pelbagai media nasional dan lokal, seperti di Koran Tempo, Kompas.id, Media Indonesia, Borobudur Writers, Sastramedia, Insidelombok.id, Kolonian.is, Lensasastra.id, Metafor.id, Kurung Buka, LiteraSIP, Sudut Kantin Project, Halimun Salaka (puisi Sundlish: Sunda-English), dan tentu masih banyak yang lainnya. Selain karya fiksi, Aldy juga menulis esai-esai reflektif serta tersiar di Kumparan, MJS Colombo, Kelas Isolasi, LSF Discourse, Zona Nalar, The Columnist, Forum Simposium, dan seterusnya. Selain itu, ia juga telah menyunting buku “Rabbit in Prison” karya Erwin Arnada, yang mengisahkan sejarah penerbitan Majalah Playboy Indonesia.
Kembali ke topik awal, sebenarnya dari zaman baheula, sudah banyak nama-nama filsuf merangkap penyair atau penyair merangkap filsuf yang kami baca-telusuri. Sebut saja misalnya nama-nama babon macam Dante Alghieri, T.S Eliot, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche, Rumi, dan tentu masih banyak yang lainnya dari tongkrongan Timur maupun Barat. Lantas apa yang spesial, dari pengarang muda dengan tato Amorfati dalam bahasa Persia di leher kirinya ini?
Boleh jadi, salah-satunya ialah dari konsep-konsep filosofis yang dikemas dan dipandang ulang dengan sudut pandang yang berbeda. Sebab, dewasa ini tak ada kebaruan yang lebih baru, selain hasil dari kerja dekontruksi-transformasi, dan Aldy mengambil peran dari persoalan demikian. Misal, sebagai contoh, puisinya yang terbit di Lensasastra.id ini:
Omnipotence Paradox
jika tuhan mahakuasa,
sanggupkah ia mencipta
batu yang dapat membuat
sisifus berbahagia?
(2022)
Omnipotence Paradox adalah paradoks klasik dalam filsafat yang sering dipakai ateis-online untuk mematahkan keyakinan kaum beragama. Paradoks tersebut menyoal, “Jika Tuhan mahakuasa, sanggupkah Ia menciptakan batu yang bahkan Ia sendiri pun tak sanggup mengangkatnya?”. Tentu, karena paradoks, baik jawaban ‘ya’ ataupun ‘tidak’ pada kenyataannya hanya menelurkan kebingungan yang memutus-asakan.
Di sinilah, pengarang yang akrab disapa Mang Aldy ini menawarkan sudut pandang baru, hasil dekontruksi-transformasi yang sudah dijelaskan di muka. Ketimbang memusingkan apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang bahkan Ia sendiri tidak sanggup mengangkatnya, lebih baik mempertanyakan sesuatu yang lebih esensial: kebahagiaan. Maksudnya, tidaklah penting apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang bahkan Ia sendiri tidak sanggup mengangkatnya. Jauh lebih penting membayangkan si Sisifus yang dikutuk secara absurd oleh Zeus untuk mendorong batu kesia-siaan dalam kekekalan itu bisa berbahagia. Dengan kata lain, Aldy mengawinkan Omnipotence Paradox dengan Mitos Sisifus à la Albert Camus di atas panggung puisi.
Puisi di atas, hanyalah satu contoh dari sekian banyak karya Genrifinaldy yang menarik dan mengusik pembaca. Sisanya, besar kemungkinan dapat kita temukan pada buku puisinya yang (menurut bocoran via-chat-whatsapp) rencananya akan terbit tahun ini, mari kita tunggu dengan saksama. Kalau ia tidak terlalu disibuk-kan oleh kerja-kerja redaktur di media tempatnya bekerja, Omong-Omong Media. Atau sebetulnya, kalau ia tidak mager dan malah lebih memilih fokus bersantai hammockan di depan Danau Lido, danau peninggalan kolonial Belanda di seberang rumahnya.
Semesta Puisi di Alam Pikiran Moch Aldy MA
Untuk mempertegas bagaimana sebenarnya semesta puisi yang dijalani sekaligus direnungi Aldy, akan kami hadirkan percakapan singkat — antara kami dan Aldy — yang semoga dapat menjawab sedikit dari beberapa pertanyaan yang mungkin akan menyelimuti pembaca budiman.
Redaksi: Mang Aldy, kita ketahui bersama, bahwa proses kreatif seseorang pada perjalannnya akan sampai pada suatu rumusan mengenai apa dan bagaimana kerja kreatif yang dijalaninya, dalam hal ini tentu puisi mulai menjadi bagian dari perjalanan kreatifmu. Sejalan dengan itu, maka perlulah kami menanyakan sekaligus menggali pandanganmu mengenai apa dan bagaimana puisi menurutmu, Mang?
Aldy: Pertama, kalau boleh jujur, sebetulnya aku tak pernah bisa—atau tepatnya, tak pernah berselera—mendefinisikan “apa puisi” secara ajeg & spesifik bla bla bla. Jika terpaksa ditodong menjawab, aku cukup curiga bahwa puisi ibarat Kotak Pandora (dalam teks aslinya, di buku “Works and Days” karya Hesiod, digambarkan sebagai guci penyimpanan). Lambat laun, kecurigaanku ini seolah-olah menemukan justifikasinya. Sebab seperti puisi, dari luar Kotak Pandora itu tampak indah & mengasyikkan, tetapi ketika dibuka alangkah brengsek ternyata isinya hanyalah kesedihan, kesengsaraan, kesepian, keputusasaan, & kesuraman-kesuraman lainnya—meski di dasarnya, tergeletak seonggok harapan. Kedua, ketimbang ‘bagaimana’, aku pikir ‘mengapa’ lebih urgen & cocok diajukan ketika menyoal puisi. ‘Bagaimana’ terdengar terlalu teknis & lebih layak dilontarkan kepada redaktur. Bagi penulis, ‘mengapa’ jauh lebih logis (& filosofis) untuk dijawab pertama kali—sisanya terserah. Lantas, mengapa puisi? Tanpa puisi, barangkali hidup yang panjang banget ini bakal terlampau mekanis, hambar, & begitu-begitu saja. Variasi perasaan yang lahir dari rahim puisi itu, besar kemungkinan, yang membikinku tetap merasa manusia. Manusia yang tak sekadar punya sistem fisiologis, tetapi punya sistem psikologis dengan beragam emosi. Tidak menjadi mayat berjalan yang nirgairah-nirhasrat. Aku percaya (meski metode ‘percaya’ tak bisa difalsifikasi secara saintifik), puisi, sebagai sesuatu yang diramu-padatkan melalui bahasa, mengandung daya ledak semacam itu. Daya ledak yang memantik nyala di dada kiri. Kalau Isa bisa menghidupkan seseorang yang tak bernyawa, maka puisi mampu menghidupkan benda, tempat, waktu, ruang—dengan cara yang sama-sama ajaib bin magis. Kabar buruknya, di ujung petang, hampir kerap kepalaku dihantui pertanyaan grandeur: masihkah puisi hidup ini? & aku belum punya jawaban, sehingga pada akhirnya cuma menyisakan keheningan yang nauseatik & memekakkan telinga.
Redaksi: Wah, sangat runut dan kompleks, ya. Lalu siapa tokoh Penyair nasional dan internasional yang katakanlah mungkin menjadi kiblat atas proses kreatifmu sekaligus yang misalnya memotivasi dirimu untuk melampauinya (dalam arti melepas diri dari kungkungan spirit dari kekurangan karya mereka untuk diolah menjadi kebaruan yang lebih baru dalam karyamu)?
Aldy: Kalau berkiblat, rasanya tidak. Pertama, baunya hiperbolis. Cukup jauh dari prinsip proses kreatifku yang dinamis. Kedua, ‘kiblat’ terkesan menjurus pada salah satu hal yang paling kubenci: taklid buta. Yang pasti (di dunia di mana kekeosan terbukti secara teori) penyair yang lumayan kusukai adalah Afrizal & Baudelaire. Alasannya cukup sederhana: aku menggilai surealisme. Ya, termasuk lukisan-lukisan Bosch, Magritte, Dalí, Kahlo, Ernst, Miró, sampai Ivan Sagita. Termasuk pula film-film Tarkovsky, Lynch, Fellini, Resnais, sampai Bergman. Itu saja. Aku tidak ingin memusingkan soal apakah nama-nama di atas (yang hampir semuanya telah menjadi arwah itu) memotivasiku ataukah tidak. Soal melepas diri, rasa-rasanya, cukup sulit. Secara total hampir mustahil. Sedikit-sedikit, bisa jadi. Sebab kerja-kerja penciptaan (menulis, melukis, menggubah, & sebagainya) niscaya saling terpengaruhi-dipengaruhi. Tak benar-benar murni personal otentik ujug-ujug laduni dari diri sendiri. Selalu ada peran eksternal, misalkan ingatan kolektif, bagaimana pengetahuan diproduksi, & seterusnya. Tapi bagaimana jika Ecclesiastes 1:9 (tak ada yang baru di bawah matahari) itu benar? Bagaimana jika semua kata pernah dikalimatkan, semua warna pernah ditumpahkan, semua nada pernah dimainkan? Maka paling-paling yang kita lakukan cuma interteks. Misalkan, mengarang ulang puisi Chairil yang berjudul Sia-sia bertitimangsa 1943: “…mampus kau dikoyak-koyak shopee!”—yang tentu saja, dengan kearifan khas Kapitalisme Lanjut zaman kiwari.
Redaksi: Sejak kapan berkenalan dengan puisi dan memutuskan untuk mencurahkan diri secara serius-terjun mendalami fenomena-fenomena yang ada di dalamnya?
Aldy: Seingat ingatanku yang pendek, pada mulanya, aku berkenalan dengan puisi ketika sedang dilanda cinta monyet. Waktu itu, pacarku (kini mantan) tak pernah absen mengunggah puisi-puisi Rumi di media sosialnya. Sebab bucin cenderung mengimitasi seseorang yang dicintainya, dengan lahap aku mulai ikut-ikutan menyantap satu per-satu puisi penyair Sufi itu. Kemudian, setiap hari rabu, kubacakan bait-bait tentang cinta & kerinduan kepadanya. Yang komikal & membagongkan terjadi kira-kira beberapa tahun setelahnya. Tepatnya setelah break up (baca: rungkad/pegat) & kusadari bahwa puisi-puisi Rumi konteksnya adalah vertikal, bukan horizontal—hubungan manusia dengan Tuhannya, bukan dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, adalah goblok menilai bahwa puisi-puisi Rumi konteksnya perihal remaja puber yang dimabuk hormon serotonin. Praktis, ada rasa malu & najis setinggi Puncak Manik bercampur di kerongkonganku (tapi di momen itulah, kumahfumi bahwa dua hati berarti “hati-hati”). Lantas dengan lekas, kutinggalkan puisi selang beberapa tahun. Tapi takdir selalu hadir dengan cara yang aneh & bakekok. Kalau Prometheus dikutuk Zeus karena mencuri api: setiap hari seekor elang datang, memakan hatinya, & malam harinya hatinya tumbuh lagi, & lagi. Maka aku dikutuk untuk kembali ke pangkuan puisi dengan menjadi redaktur fiksi & membaca puisi hampir setiap hari di media tempatku bekerja. Ya, tidak beda jauh. Hubunganku dengan puisi, agak putus-nyambung. Bisa jadi persis seperti ketika aku men-skip lagu-lagu Pink Floyd, Khruangbin, Radiohead, The Smiths, Tame Impala, & Muse di Spotify & menyesali betapa tolol telah melewatkan secuil kenikmatan. & demi melipur kekesalan, kuputar on repeat—agar puas. Omong-omong, meski senin sampai jumat aku membaca puisi, tetapi aku tidak pernah benar-benar serius mencurahkan diriku di puisi, khususnya penulisan. Kujadikan menulis puisi hanya sebagai pariwara. Staycation. Sepotong liburan yang menyenangkan & menggirangkan. Mirip orang-orang Jakarta yang mengunjungi Puncak Bogor hanya di akhir pekan. Singkatnya, meminjam Rimbaud, dua musim di surga di antara lima musim di neraka. Seseorang mungkin bertanya: “mengapa tak sekalian tujuh musim di surga?”—sebab surganya menulis puisi hanya untuk pikiran-perasaan, bukan perut. Penyair tua bangka itu tahu, lapar adalah maut, lebih nyata dari metafora. & menggantungkan hidup dari menulis puisi ekuivalen dengan menggantung diri. Kalau menjadi redaktur puisi, mungkin lain cerita. Atau mungkin sama saja. Entahlah. Hanya Sumedang yang tahu.
Redaksi: Sekarang kita beralih ke alam pikiran dan fenomena filsafat yang menarik minatmu. Pertanyaan yang akan kami berikan masih sama fokusnya. Apa dan bagaimana Filsafat menurutmu, Mang?
Aldy: Sesekali, aku menduga-duga, memakai sedikit istilah Zapffe, filsafat cuma efek domino dari evolusi manusia yang bergerak ke arah yang lebih jauh (& salah). Semacam keberlebihan yang menghasilkan celaka-celaka. Menjadikan pikiran terlalu canggih & tajam. Aku percaya, lidah sepanjang tiga inci yang telah dibumbui filsafat bisa dengan mudah membunuh seseorang dengan tinggi enam kaki. Ia adalah pedang yang menebas hampir segala. Filsafat adalah pedang berbilah dua. Satu bilah mengarah pada realitas yang tidak dikupas, satu bilah lainnya mengarah pada penggunanya. Dengan demikian, berfilsafat menjadi kesia-sian yang membahayakan (seperti partikel “sia-sia” dalam manusia-manusia). Rawan diserang pikiran berlebih & kecemasan konstan. Meminjam teks Cioran yang diubah agar sesuai konteks: filsafat lebih dari sekadar duri, ia adalah belati dalam daging. Tanpa filsafat, tentu, hidup tentu akan baik-baik saja. Adem ayem. & aku ingin kontra dengan Popper, menurutku, filsafat bukan kegiatan yang perlu & penting. Tentu tidaklah penting bagi seorang pengusaha UMKM yang berdagang di trotoar untuk mengetahui Dualisme Tubuh & Jiwa à la Descartes, Taruhan Pascal, Paradoks kapal Theseus, Dilema Etika dalam Masalah Troli, & sebagainya. & boleh jadi Wittgenstein benar, “para filsuf sering kali seperti anak kecil, yang pertama kali mencoret-coret garis acak pada selembar kertas dengan pensil, & kemudian bertanya kepada orang dewasa, ‘Apa itu?’”. Alias hanya menambah-nambah masalah. Seni mempersulit-memperumit kehidupan yang sejak awal sudah sulit-rumit. Maka lambat laun, aku ingin merevisi puisi Heine, “filsafat itu baik, tidak berfilsafat lebih baik; tapi tentu saja, hal terbaik adalah tak pernah mengenal filsafat sama sekali.” & juga kutipan Sophocles yang beken disadur Gie, “nasib terbaik adalah tidak mengenal filsafat, yang kedua mengenal tapi tidak berminat mendalami, sedang yang tersial adalah berumur panjang & mati sebagai filsuf.” Rasa-rasanya begitu. Semakin dekat aku dengan filsafat, semakin jauh aku dengan orang-orang sekitarku. Aku terasa semakin alien (atau ‘Arpeggi’, dalam kamus besar bahasa Thom Yorke. Meski begitu, pada akhirnya, filsafat tetaplah laboratorium pikiran-pikiran serampangan. Tempatku mengasuh anak bawel dalam diriku: bereksperimen & mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan naif dengan segenap keseriusan—yang barangkali di ujung langit pun tiada jawabannya. Semoga Dostoevsky benar, jiwa disembuhkan dengan bersama/menjadi anak-anak. Amin.
Redaksi: Lalu, siapa tokoh Filsuf nasional dan internasional yang menjadi kiblatmu sekaligus yang memotivasi dirimu untuk melampauinya (dalam arti melepas diri dari kungkungan spirit dari kekurangan karyanya)?
Aldy: Dengan tato amorfati dalam aksara Persia di leher sebelah kiri, besar kemungkinan, seseorang mengira aku Nietzschean tulen. Wajar. Tapi tidak, aku bukan pengikut filsuf sinting asal Jerman itu. Kalau pernah terinspirasi, mungkin iya. Ia hanyalah satu dari sekian. Ada banyak filsuf yang cukup memengaruhiku: Gautama Buddha, Kierkegaard, Sartre, Epicurus, de Unamuno, Marx, Schrödinger, Russell, Zhuangzi, Baudrillard, Beckett, KL Supelli, & yang tak bisa kusebutkan satu per satu. Tapi filsuf yang benar-benar menginspirasiku adalah Diogenes dari Sinope. Pertanyaannya kemudian, apakah aku termotivasi untuk melampauinya? Oh, tentu tidak. Aku tidak berhasrat untuk masturbasi di Pasar Cigombong, menenteng lentera di siang bolong, atau pergi ke sebuah diskusi Platonis sembari membawa ayam yang telah dicabuti bulu-bulunya kemudian mengatakan, “wahai orang-orang dungu… inilah manusia! hewan berkaki dua & tidak berbulu.” Percayalah, aku tidak sesinis & sesinting itu. Aku cuma mencintai keberaniannya dalam mengolok-ngolok standar kewarasan dari norma sosial. Lagipula, apalah arti karya-karyaku yang tak seberapa itu. Terlalu receh. Remeh-temeh yang nirmakna. Paling banter cuma komposisi dari sedikit proton, sedikit neutron, sedikit elektron, & banyak moron. Mendengungkan kembali Bataille, “sebenarnya kita hanya memiliki dua kepastian di dunia ini: kita bukanlah segalanya & bakal mati.”
Redaksi: Sejak kapan berkenalan dengan filsafat, dan memutuskan untuk mencurahkan diri secara serius-terjun mendalaminya?
Aldy: Kira-kira umur 14 tahun, SMP kelas dua. Waktu itu, kawanku yang lebih tua—sebut saja P—meminjamkanku Dunia Sophie-nya Gaarder. Kemudian aku mereguk The Little Prince karya de Saint-Exupéry, The Unbearable Lightness of Being karangan Kundera, sampai The Trial buah pena Kafka. (Karya-karya yang kusebut itu, kuanggap sebagai kawin silang Filsafat & Sastra). Dengan kata lain, aku mengenal filsafat melalui pintu sastra. & seperti mereguk air laut, semakin kureguk semakin dehidrasi. Aku tak pernah puas. & seperti puisi, aku pun tak pernah sepenuhnya mencurahkan diriku kepada filsafat. Meskipun aku hampir selalu teringat percakapan dari serial TV Malcolm in the Middle episode ketigabelas berjudul ‘Rollerskates’, “son, do you know, once you start there’s no going back? … this means total commitment. once you begin the path, there is no leaving the path. are you sure you’re ready for that? i mean really ready? (nak, tahukah kau, sekali memulai, tidak ada jalan untuk kembali? … ini berarti komitmen total. sekali kau memulai, tidak ada jalan untuk meninggalkan jalan itu. apakah kau yakin, kau sudah siap untuk itu? maksudku benar-benar siap?)”. Ya, meskipun, konteksnya adalah tentang belajar bermain skateboard. Tapi bukankah, dalam hal apapun, dibutuhkan komitmen yang total & tidak setengah-setengah? Di titik ini, aku terbesit petuah kawanku di Omong-Omong Media, Pak Guf. Ia menyoal tentang Kutukan Platipus. Menurutnya, hewan tersebut multitalenta tapi tidak benar-benar ahli dalam suatu hal. Alias jack of all trades & a master of none, dalam tutur Shakespeare. Platipus bisa berenang tapi tidak ngebut, berbisa tapi tidak mematikan, bisa menyala dalam gelap tapi tidak terlalu berguna… bisa banyak hal tapi tidak pandai-pandai amat. Aku merasa seperti platipus. Aku tidak fokus pada satu hal. Terlalu banyak yang kugerus. Sisanya, aku hanya menyangka diriku perfeksionis sekaligus prokasinator—artinya, secara terus menerus, mencemasi kualitas karyaku yang bahkan tak tahu kapan akan kuselesaikan. Kembali pada filsafat, pada puncaknya, di mataku, ia bukan soal lomba bijak-bijakan, love of wisdom & sebagainya. Tapi soal menerima-menghargai karunia sekaligus kutukan Tuhan kepada manusia: akal, kesadaran, & tetek bengeknya.