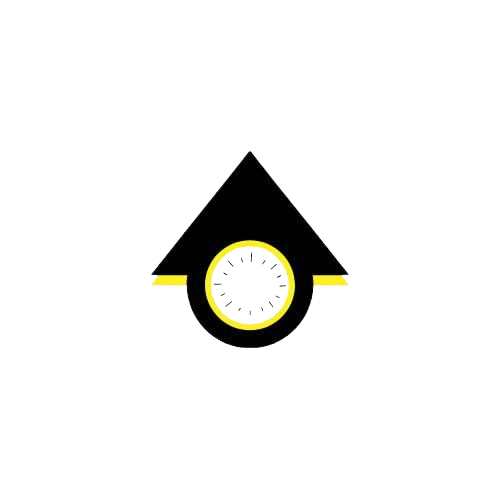foto: fahriza nugraha
Hubungan antara sastra dan musik, kami rasa, merupakan ikatan yang begitu erat dan telah terjalin sejak zaman baheula, yang mana biasanya muatan isinya menceritakan tentang kehidupan para Raja atau keluarga sanak-saudara istana, mitos-mitos masyarakat, dan legenda suatu daerah, atau suatu bangsa umumnya. Keduanya merupakan bentuk seni yang mengeksplorasi emosi, ide, dan pengalaman empiris-rasio dalam diri manusia.
Ketika berbicara tentang sastra dan musik, bayangan kami tertuju pada masa di mana nyanyian-nyanyian ritual dan lagu-lagu rakyat menjadi bagian dari nilai kebudayaan, misalnya kami ambil contoh Carita Pantun dalam kebudayaan Sunda. Carita Pantun dilantunkan oleh Juru Pantun, yang mana terjalin perpaduan-kelindan sastra lisan yang diwarisi secara turun-temurun dengan alat musik kacapi sebagai media untuk menjadikannya lantunan melagukan cerita, misalnya tentang cerita Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi, dan sebagainya.
Dengan demikian, kerja kolaborasi semacam itu sudah sejak lama telah dijalani oleh leluhur kita dalam mengolah kerja keseniannya, lewat proses membangkitkan berbagai perasaan: seperti sedih, gembira, marah, cinta, derita, dan bahkan emosi lainnya. Melalui kata-kata yang disusun menjadi sebuah cerita, dan diolah melalui nada, melodi, ritme menjadi irama lagu, hubungan sastra dan musik dapat menyampaikan pesan perasaan serta pikirannya secara mendalam kepada pembaca dan pendengarnya.
Maka, cerita-cerita pantun telah memainkan peranan penting perkembangan sastra dan musik dalam tubuh kebudayaan Sunda pada zamannya. Seperti halnya Troubadour yang telah membentuk budaya musik dan puisi di Eropa pada abad pertengahan. Sebagaimana Dante Alighieri mencatat dalam karyanya yang berjudul, De vulgari eloquentia, yang menganggap lirik troubadour sebagai fictio rethorica musicaque poita: fiksi retorik, musikal dan puitis.
Tentu saja, masih banyak studi kasus dan contoh lainnya untuk kita bisa menyusuri apa dan bagaimana jalan panjang kelindan sastra dan musik dalam tradisi istana maupun rakyat kecil pada zaman baheula, yang mana pada perkembangannya persoalan hubungan sastra dan musik itu diteruskan dari generasi ke generasi, mengalami perubahan gaya, tema serta tujuan, pembauran antar kelas sosial, dan seterusnya. Kemudian kini kita mengenalnya sebagai Folk. Sama halnya dengan istilah balada rakyat, contoh utama dari karya sastra lisan yang ditemukan di berbagai tradisi folk, salah satunya balada Indonesia yang dikenal dengan pantun atau gurindam. Namun rasanya akan sulit untuk kita menentukan secara ajek, sejak kapan, di mana, dan siapa orang yang pertama kali melakukan kolaborasi atau menghubungkan kerja sastra dan musik.
Yupsss! Berhubungan dengan sedikit pengantar di atas, pada edisi #2 Persona Pilihan Halimun Salaka kali ini, kami memilih nama Fahriza Nugraha, seorang pengarang sekaligus musisi yang karya-karyanya sangat menggembirakan kami khususnya sebagai pembaca tulisannya dan pendengar lagunya.
Wahana Makna Fahriza Nugraha
“Jikalau aku mendengar lagu olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu olesio. Aku mendengar Indonesia.”
Begitulah penggalan puisi Bung Karno berjudul “Aku Melihat Indonesia,” yang menggambarkan tentang kemerdekaan. Jadilah penggalan tersebut sebagai jembatan di jalan perkenalan dengan Fahriza Nugraha yang merdeka bercerita lewat sastra dan musiknya. Memangnya siapa sih Fahriza Nugraha?
Secara singkat, sebab ia sendiri tak ingin memberikan penjelasan detail tahun dan bulan lahirnya, maka beginilah mungkin perkenalannya: Fahriza Nugraha merupakan pengarang dan musikus serampangan yang lahir di bawah langit muram kota Bogor. Kini singgah dan bekerja di kota kelahirannya sebagai juru seduh di kedai kopi miliknya sendiri bernama, Sapa Remaja. Karya-karyanya antara lain, Buku: Catatan Kobra (2018), Bisakah Kunci Terbuka (2020). Album: Amung, Ambung, Banglas (2018), Petang Tiga Puluh (2019), Bunga dan Roti (2023), dan karya terbarunya berjudul, Sebelum Kau dan Aku Mati (2024). Ia juga membidani beberapa proyek musik lainnya, seperti Medical Cleopatra, Suara Suara, dan La Tappa.
Pembaca budiman tak perlu jauh-jauh mencari di mana keterhubungan antara kebebasan Fahriza dengan kemerdekaan (pada kutipan puisi) yang digambarkan Bung Karno di atas. Juga tak usahlah pusing-pusing dengan kaca-mata apa jika kita hendak bekenalan dengan karyanya. Sebab bila membaca dan mendengar olahan karya Fahriza, boleh dipastikan bukan lagi sosok Fahriza yang kita dapati, melainkan nilai-nilai kebebasan. Maka meminjam salah satu penggalan liriknya lagunya yang berjudul, Kita, Hidup (dalam album Bunga dan Roti): “udara kebebasan terhirup panjang/ kita terlahir di belahan bumi/ mengais tugas dari sang pencipta”. Ya, memang begitulah kebebasan bekerja dalam menikmati kehidupan dan kebebasan dalam membikin sebuah karya untuk kehidupan, tetap saja di setiap kejadian-kejadian kita tetap akan membersamai Tuhan.
Narasi dan cerita yang juga ditawarkan oleh Fahriza dalam novelnya, Bisakah Kunci Terbuka, membawa luapan ekspresi dari kehidupan sehari-sehari, emosi personal, yang terkadang disisipi peristiwa masyarakat kecil di persimpangan sejarah dan kenangan kelam: “Arumi menerawang ke arah dedaunan di pekarangan yang tersapu angin. Ia membebaskan pikirannya mengawang-awang ke mana saja. Dan lagu Like A Rolling Stone yang dibawakan Bob Dylan dari pemutar kaset, jadi pengiring lamunan si perempuan yang selalu ingin bekerja secara maksimal.” Kutipan cerita itu mulanya disebabkan ketika Arumi mendapat tugas mata kuliah Investigasi Surat Kabar & Majalah untuk menginvestigasi kasus mengenai kawin kontrak yang ada di daerah Puncak. Selanjutnya, cerita membawa Arumi yang tak ingin membongkar kasus pelacuran yang ecek-ecek, seperti pijat plus-plus, lokalisasi, dan para PSK kaki lima, menurutnya itu semua biasa. Setelah mempertimbangkan semua itu, Arumi dengan tegas memutuskan bahwa, “Aku harus menyamar sebagai pelacurnya. Aku harus mendapatkan target seorang pejabat!.”
Bagaimana akhir dari perjalanan Arumi itu? Tentu kami tak akan membeberkannya secara gamblang utuh di sini, agar pembaca sekalian membaca sendiri cerita lengkap dalam bukunya. Kami hanya akan mengajak pembaca untuk mendengarkan lagunya yang berjudul, Rabu (dalam album barunya, Sebelum Kau dan Aku Mati), yang mana menurut hemat kami memberikan kemungkinan lain kisah dan perjalanan Arumi, yang tengah melewati kemungkinan-kemungkinan/ menjelajahi keterasingan/ mustahil bila tak berkemas, membusuk lalu mati mengeras.
Seikat penggambaran hasil membaca dan mendengar karya Fahriza di atas, akan membawa kita pada dimensi “kontemplasi bukan sembarang kontemplasi,” yang pada dasarnya mengais berbagai fenomena-fenomena di dalamnya: baik atau buruk, cinta atau benci, bahagia atau sedih, dan lain sebagainya. Maka dengan mempertimbangkan dimensi kontemplasi, kita harus menempuh nilai kebebasan sebagai manusia—agar lebih dekat dengan kesadaran akan entitas yang jauh lebih besar-berkuasa dari diri kita sendiri. Itulah mengapa, Fahriza sendiri menyebut kehidupan berkeseniannya adalah tidak lain sebagai cibiran terhadap kehidupan budaya modern. Ia bahkan beranggapan “budaya pop adalah Tuhan” untuk menggambarkan situasi di pintu gerbang kesenian yang banyak disesaki orang-orang.
Sejalan dengan itu, untuk mempertegas bagaimana pandangannya tentang sastra dan musik, muatan makna apa dalam perjalanan proses kreatif dan karyanya, mari kita simak percakapan singkat hasil omong-omong fufufafa Redaksi dengan Fahriza Nugraha.
Mendengar Fahriza Nugraha Bercerita
Redaksi: Sebelum masuk ke hal-hal mendalam perjalanan proses kreatifmu. Kami penasaran tentunya, dan perlu mengorek-ngorek pandanganmu terlebih-dahulu. Apa dan bagaimana menurutmu sastra dan musik itu, Mang?
Fahriza: Hahaha! Pertanyaan di poin pertama sudah cukup sulit. Saya tidak bisa menjabarkan hal itu dengan sedemikian rinci dan indah. Apalah yang saya ketahui tentang keduanya, tak jauh seperti Toilet. Bagi saya sastra dan musik memiliki kaitan yang sangat erat. Bahkan tidak bisa dipisahkan. Saya menganggap bahwa keduanya adalah Toilet, karena Toilet adalah tempat di mana saya bisa menelanjangkan diri saya untuk berekspresi sedemikian liar dan bebas. Hmmm, bukankah hanya di Toilet orang-orang bisa dengan bebas bercerita dengan dirinya? Mandi sembari bernyanyi? Buang air besar sembari memotret umpatan yang bagus? Banyak hal yang bisa dicurahkan di Toilet. Dan bagi saya, musik dan sastra sama seperti Toilet. Setidaknya untuk saya pribadi.
Redaksi: Kita tahu, Mang. Lingkungan akan sangat memengaruhi minat dan bahkan tujuan hidup seseorang, entah apapun bidang yang dijalaninya. Bagaimana sih mulanya dirimu tertarik pada dunia sastra dan musik?
Fahriza: Betul, lingkungan sangat berpengaruh. Dan ketertarikan saya kepada sastra dan musik tak lain dari lingkungan saya sendiri. Khususnya keluarga. Sejak kecil saya sudah akrab dengan musik dan sastra. Ibu dan ayah saya yang secara tidak langsung menyumpal saya dengan mereka. Sialan, ya. Ibu saya seorang pustakawan. Dan ayah saya walau tidak bekerja di ranah musik atau sastra, tapi beliau penikmat musik dan sastra. Beliau kerap menulis puisi dan bermain musik di waktu senggang. Dan kedua orang tua saya terbilang candu kepada buku dan musik. Setiap pagi musik mengalun dari tape deck sebagai pengiring sarapan, dan begitu saat malam hari saat kami beristirahat sembari mengerjakan tugas atau membaca buku. Itu asal mula saya jadi ikut menyukai sastra dan musik. Ditambah, lingkungan rumah pun begitu. Sebagai anak yang tumbuh di era millenium dengan pengaruh MTV yang sangat kuat.
Lingkungan rumah atau kampung di era itu memang tengah gandrung musik. Selama ibu dan ayah saya bekerja, saya menghabiskan waktu bersama para tetangga yang berusia lebih di atas saya. Bisa dikatakan mereka abang-abangan, dan dari mereka pula wawasan musik saya bertambah. Setiap hari musik tidak pernah putus di telinga saya. Dan satu faktor yang mendukung lagi, almarhum paman–adik dari ibu saya–di zaman itu miliki toko musik yang menjual-belikan kaset, laser disc, dan VCD. Nyaris setiap minggu saya habiskan waktu akhir pekan di sana. Membantu paman merapikan kaset sesuai genre dan VCD sesuai abjad. Dari sana juga banyak referensi yang saya dapatkan. Bahkan rilisan musik yang tidak diulas oleh media mainstream. Katakanlah rilisan musik independen lokal atau bahkan luar dengan genre aneh yang biasanya dijual oleh remaja yang sedang kebelet pengen giting. Dan saya selalu tertarik dengan rilisan kaset itu karena memiliki gambar sampul yang menarik.
Redaksi: Momen-momen penting perjalanan hidup seseorang akan sampai pada suatu rumusannya masing-masing, katakanlah semacam pilihan dan tujuannya. Mengenai itu, kapan dirimu mulai serius menekuni dunia sastra dan musik ini?
Fahriza: Saya tidak pernah menganggap bahwa saya sedang menggeluti musik dan sastra secara serius. Ini hanyalah media untuk saya menyampaikan pesan dan bersenang-senang. Ini terbukti dari saya yang bersikap ogah masuk ke dalam industri tersebut. Ada satu gagasan yang saya pilih dari kenapa saya berkarya, yakni ingin meledek batasan-batasan yang diciptakan oleh industri sastra dan musik yang picik dan terlalu banyak aturan. Pilih kasih. Dan omong kosong. Hahaha, maaf! Saya melantur, ya? Oke, saya jawab poin ini dengan cukup serius deh.
Saya tidak tahu pasti kapan saya mulai serius menekuni sastra dan musik. Tapi mungkin Tuhan tahu itu kapan. Singkat ingatan saya, sejak SD saya sudah mulai menulis. Setiap hari saya rajin menulis jurnal. Dan setiap mendapati tugas mengarang, saya adalah siswa yang paling merasa beruntung terhadap tugas itu. Saya menikmati kegiatan menulis sejak saya SD. Saya pikir ada suatu hal yang membuat saya menjadi lebih dekat dengan diri sendiri, dan lebih menghargai suatu momen ketika saya menulis. Namun saat masuk SMP saya menanggalkan kegiatan menulis. Saya memilih untuk berekspresi lewat gambar di media tembok. Saat itu mungkin saya disebut sebagai anak yang melanggar hukum sebab gemar melakukan aksi vandalisme. Tapi saya beranggapan bahwa menggambar di tembok adalah pilihan tepat untuk menyampaikan pesan tanpa mesti tersorot siapa pembuatnya. Dan yang membikin saya tertarik untuk mencoba dunia street art adalah video game Playstation berjudul Getting Up, dan beberapa referensi lain dari internet.
Di masa SMP, saya mengerjakan banyak mural yang sarat akan kritik sistem pendidikan di tempat saya menimba ilmu. Terlalu banyak kejanggalan yang berlangsung di sana. Saya melakukan propaganda dalam bentuk mural sebagai upaya menyadarkan teman-teman dan membuat pihak sekolah sadar akan apa yang sedang mereka perbuat. Isu yang kerap saya angkat yakni pembagian kelas sesuai ekonomi orang tua siswa, metode pembelajaran yang tidak sesuai dan merata, tindak korupsi dan gratifikasi yang sering terjadi saat hendak pembagian raport, hingga pelecehan seksual. Semua saya bahas dalam gambar berupa mural dan poster. Hingga pada akhirnya, saya tertangkap dan diancam dikeluarkan dari sekolah. Namun setelah bernegosiasi yang melibatkan banyak pihak akhirnya saya tidak dikeluarkan. Malah, kepala sekolah di SMP tersebutlah yang diganti. Dan dari cerita itu sampai sekarang saya pun masih heran kenapa saya berani melakukan itu. Walau saya tidak sendiri, setidaknya 4 bocah ingusan umur belasan kenapa bisa berpikir untuk melakukan hal itu? Hahaha.
Balik ke topik pertanyaan. Di masa SMP selain saya sedang gemar-gemarnya menggambar, saya pun membentuk band. Bukan hanya sembarang masuk studio untuk genjrang-genjreng saja, tapi band saya sudah mampu merilis 3 lagu. Crazy Channel dipilih sebagai nama dari band tersebut dengan genre Pop Punk yang terpengaruh dari Blink 182. Sebetulnya di zaman SD kelas 6 saya juga pernah membentuk band. Asal-asalan memang. Namanya Ekliptika. Sebuah nama yang saya ambil dari buku fisika yang berarti lintasan yang dilalui matahari. Saat itu saya punya akses khusus untuk masuk studio musik karena banyak abang-abangan yang saya kenal yang bekerja di studio musik itu. Lokasinya pun tidak jauh dari tempat saya sekolah. Jadi saya kerap mengajak rekan-rekan saya untuk main musik di sana. Pertama kali kepengen main musik karena melihat musik video Red Hot Chilli Peppers dan menganggap bahwa sangat keren jika bermain musik.
Seusai bubar dengan Crazy Channel karena alasan perpindahan sekolah di masa SMA saya tidak membuat band. Lebih tepatnya tidak membuat band yang merilis lagu. Saat itu saya hanya iseng bersama teman-teman di dalam studio, dan memainkan lagu Social Distortion, NOFX, Rancid, Ramones, dan band-band Punk Rock lainnya. Pada saat SMA sekiranya kelas 2, saya mulai tertarik lagi untuk menulis. Saya mulai mencoba menulis cerita pendek. Dan ada satu cerpen yang saat itu saya kirim ke media lokal dan berhasil diangkat. Alasan kenapa saya balik menulis karena beberapa hal. Yang pertama saya merasa bosan dengan majalah dinding di sekolah saya yang tidak pernah ada pembaharuan. Padahal itu salah satu media informasi yang asyik. Kemudian dengan inisiasi dan izin untuk menjadi juru mading saya mulai mengisi cerpen, artikel, opini, poster bergambar, yang setiap minggunya menghidupi majalah dinding di sekolah (di masa SMA saya tidak terlalu bandel seperti SMP. Jadi saya sudah melupakan cara-cara vandalisme dan lebih memilih untuk melakukannya secara legal). Bahkan saya pun pernah mencetak zine yang mengulas seputar sekolah. Macam majalah, ada rubrik tokoh yang memuat para siswa yang berprestasi juga siswa-siswa bandel dan unik. Rubrik kuliner yang berisi rekomendasi makanan kantin. Rubrik destinasi yang berisi spot nongkrong di lingkungan sekolah saat waktu istirahat. Dan rubrik asmara yang berisi gosip pasangan, biro jodoh, dan tempat curhat.
Oya, faktor lain yang membikin saya mulai mencoba menulis bukan hanya sekadar tentang majalah dinding. Pun juga berkat dorongan teman saya. Tika namanya. Ia rekan saya sejak SMP namun baru dekat saat kami sudah SMA. Di suatu waktu, kami berdua bertemu dan membuka obrolan terkait bakat minat. Mengingat sebentar lagi kami akan lulus sekolah. Padahal saat itu kami masih duduk di bangku SMA kelas 2. Entahlah. Tika memang selalu berusaha membuat saya memikirkan tujuan untuk digapai. Dan baginya, saya memiliki bakat minat di ranah kesusastraan. Waktu itu Tika membuka buku jurnal saya yang kemudian membikin ia berkata bahwa saya berbakat dalam menulis. Lalu ia berkata, “kalau kamu pengen ketemu aku di minggu depan, kamu harus menyelesaikan satu karangan cerita pendek. Jika tidak, ya tidak ada pertemuan.” Saya sepakat dan dari tugas itulah kemudian saya mulai membiasakan diri untuk menulis karangan cerita. Hingga pada akhirnya saya betul-betul tertarik pada ranah kesusastraan.
Selepas SMA, saya berniat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Saya yang tertarik pada isu-isu budaya berkeinginan untuk masuk jurusan Antropologi. Namun tidak mendapat restu dari orang tua sebab jarak dan biaya. Pada akhirnya saya lanjut studi di salah satu kampus swasta di Kota Bogor. Saya mengambil jurusan jurnalistik sebab alasan karena saya gemar menulis dan miliki pertanyaan besar terhadap geliat industri media massa. Di masa perkuliahan gaya penulisan saya semakin terbentuk. Saya menggabungkan metode-metode penulisan berita untuk tulisan fiksi saya. Bisa disebut sebagai gaya jurnalisme sastra yang dikenalkan Thomas Wolfe. Saat masa kuliah itu, saya berhasil merampungkan dua novel yang kemudian diterbitkan secara independen. Di antaranya Catatan Kobra (2018), Bisakah Kunci Terbuka (2020).
Bukan hanya menulis, di masa perkuliahan saya mulai aktif kembali bermusik. Proyek duo folk saya bernama Jembatan Merah terbentuk saat saya baru saja masuk kuliah di tahun 2015. Dan telah merilis Album EP. Setelah itu, tahun 2017 saya memutuskan untuk bersolo karir dengan nama Diserojakan. Yang melahirkan album Amung, Ambung, Banglas (2018), Petang Tiga Puluh (2019), Bunga dan Roti (2023), Sebelum Kau dan Aku Mati (2024). Dan beberapa proyek musik lainnya seperti Medical Cleopatra, Suara Suara, dan La Tappa.
Redaksi: Sangat runut dan mengesankan! Tadi dirimu berbicara tentang kenangan dan peristiwa pertemuan dengan sastra dan musik dari semasa SD sampai ke masa kuliah. Sejalan dengan itu, Mang, apa yang menjadi motivasi terbesar dirimu untuk terus berkarya di bidang sastra dan musik? Lantas apa yang ingin dirimu capai dari kedua bidang ini?
Fahriza: Jawabannya mungkin akan terkesan sensitif. Atau bahkan naif? Haha!
Jadi begini, motivasi terbesar saya dalam berkarya tak lain hanya sebagai lelucon. Semacam meledek industri arus utama dan geliat orang-orang konservatif di dalamnya. Diserojakan adalah sikap bahwa untuk melahirkan karya kamu tidak perlu miliki skill yang wah dan tampang yang necis. Dan rasa jenuh saya melihat sastra dan musik yang begitu-begitu saja. Tidak ada ledakan pembaharuan. Semua manut sesuai apa yang diinginkan industri dengan dalih permintaan pasar agar karya laris manis. Semua mengantri di arus utama. Berharap menjadi tokoh besar yang diagung-agungi semua orang. Tuhan adalah budaya pop di era ini. Tidak ada yang murni. Semua hanyalah pengulangan dan kepalsuan terhadap hal-hal keindahan. Sebagai penikmat seni Avant-Garde, pengagum gerakan kaum Beat Generation, dan terkena pengaruh ideologi Punk sejak dini saya memilih untuk berjalan di seberangnya. Karya yang saya ciptakan berasal dari keterbatasan dan ketidakmungkinan yang dikerjakan secara mandiri. Dan pencapaian saya, bukan tentang karya saya yang dikenal banyak orang dan dinikmati. Tapi publik harus menerima karya yang berbeda. Tidak ada lagi cemooh terhadap karya aneh. Ini membuka kesadaran wawasan seni yang luas dan bebas. Tidak perlu terpengaruh dengan produk-produk industri besar yang berdampak pada asumsi bagus dan jelek. Ceileh, saya melantur, ya?
Redaksi: Dirimu menekankan tentang pengaruh sekaligus pengagum kaum Beat Generation dan pengaruh Punk sejak dini, adakah sastrawan dan musisi baik nasional maupun internasional yang secara khusus menjadi kiblatmu, atau dalam arti lain katakanlah yang telah memicu geliat proses kreatif pengkaryaanmu sekaligus memengaruhi cara pandanganmu terkait cara kerja menempuh-memandang sastra dan musik?
Fahriza: Aih, sebetulnya saya selalu menghindari pertanyaan semacam ini yang mengarah ke dapur saya. Tapi tak apalah saya jawab. Tokoh yang memengaruhi saya di sastra mulai dari luar negeri sudah pasti gerombolan beat generation. Antara lain Jack Kerouac, Allen Ginsberg, dan Bob Dylan yang ini juga punya kaitan dalam musik. Selain itu, saat saya masih SD saya pengagum karya Enyd Blyton dan Agatha Christie. Dan penulis luar lainnya yang memengaruhi proses kreatif saya dalam menulis yakni Roberto Bolano, Charles Bukowski, Etgar Keret, Lidya Davis, Sylvia Plath, Franz Kafka, Mieko Kawakami, Haruki Murakami, Albert Camus, dan Jean-Paul Sartre. Dan untuk Indonesia, mungkin saya hanya sebatas sebagai penikmat setia karya-karyanya. Seperti Aan Mansyur, Oka Rusmini, Nh. Dini, Ayu Utami, Andrea Hirata, Hamsad Rangkuti, Afrizal Malna, Djenar Maesa Ayu, dan tentu Pramoedya Ananta Toer dan Chairil Anwar. Oya, tapi ada satu penulis Indonesia yang punya cerita berkesan untuk saya dan proses penulisan saya. Yakni Marienna Katoppo. Lewat bukunya yang berjudul Raumanen pemberian dari ibu saya, membikin saya miliki pandangan lain untuk menulis cerita. Itu berlangsung saat saya masih SMA.
Sedangkan di musik, musikus atau band yang memengaruhi saya sehingga saya berani dan harus bermain musik tak lain adalah Daniel Johnston. Ia musikus gila yang produktif walau industri tidak peduli dengannya. Musiknya menjadi referensi untuk band-band besar. Dan beberapa nama lain seperti Mike Ness, Bob Dylan, Johnny Cash, dan band-band punk bawah tanah yang membentuk sikap saya dalam bermusik. Kalau di Indonesia sih, ya, band arus utama yang saya suka itu slank. Itu sudah sejak saya berusia hitungan jari sebab dikenalkan oleh abang-abangan. Bagi saya slank luar biasa karena bukan lagi memperkenalkan soal musik. Melainkan gaya hidup. Di era itu nyaris semua anak muda mengadopsi kehidupan macam slank. Slank punya komunitas yang kuat dan segala produksi pun dikerjakan secara DIY. Segitu saja kali, ya? Kalau tentang genre musik yang memengaruhi sih lumayan banyak. Sebut saja Punk Rock, Rockabilly, Country, Folk, Grunge, hingga musik Outsider Avant-garde dan ya pokoknya semua musiklah saya dengar tidak menutup pengecualian dangdut dan melayu. Semua saya dengar.
Redaksi: Nama-nama yang dirimu sebut, baik sastrawan maupun musisi, sedikit banyaknya kami lihat sangat memengaruhi cara pandangmu, dan itu satu hal yang memang sudah sejak zaman ke zaman dalam perjalanan panjang proses kreatif seseorang akan saling memengaruhi dan bahkan pada akhirnya akan saling melampaui. Lalu bagaimana dirimu membagi waktu antara berkarya di bidang sastra dan musik? Misalnya, apakah ada tantangan khusus yang dirimu hadapi ketika menjalani kedua bidang ini?
Fahriza: Sebetulnya keduanya saling melengkapi. Saya tidak memporsi antara kegiatan menulis dan bermusik. Sering ketika saya tengah menulis, di sela-sela waktu buntu, kemudian saya mengalihkan pikiran ke musik. Keduanya begitu jadi hiburan untuk saya. Bahkan tak sedikit lagu yang saya ciptakan liriknya dicomot dari puisi-puisi yang saya tulis. Atau rangkuman dari alur cerita pendek yang saya karang. Kurang lebih begitu.
Redaksi: Nah, berhubungan dengan itu, Mang, apa saja hambatan yang pernah dirimu alami dalam mengembangkan karya di Bogor?
Fahriza: Hahahahaha! Apakah ini mesti dijawab? Seperti yang kita ketahui bahwa Bogor hanyalah kota kecil persinggahan. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Atau apa yang kita harapkan di kota ini? Tidak ada. Semua menggantungkan mimpi dan nasibnya ke ibu kota. Tapi saya sendiri gak tertarik-tertarik amat untuk mengemis ke ibu kota. Biarkanlah karya saya hanya menjadi jejak bahwa saya pernah hidup di kota Bogor. Saya tidak menyalahkan sedemikian bulat terkait tata letak kota, atau para warganya sendiri yang belum melek dalam apresiasi karya? Entahlah. Saya pikir terlalu banyak PR untuk mengembangkan kota ini, setidaknya dalam sarana dan prasarana kota.
Redaksi: Kita masuk ke persoalan inspirasi, metode, atau bahkan cara menjalani proses kreatifmu dalam berkarya, yang pada dasarnya tentu memiliki perbedaan dan gayanya masing-masing tiap individu. Bagaimana proses kreatif dirimu dalam menulis karya sastra dan menciptakan musik beserta liriknya?
Fahriza: Inspirasi dan metode dalam proses kreatif saya dapatkan dari tokoh-tokoh yang saya kagumi. Biasanya saya mencari referensi dari seniman bawah tanah. Mereka jenius. Namun tidak pernah tersorot oleh media massa. Mungkin karena tidak menarik perhatian, tidak punya jumlah pengikut yang besar, tidak mampu membuat produk/cetakan media massa menjadi laris. Hahaha. Maaf saya gemar melantur ke sana ke sini. Intinya dalam proses kreatif yang saya langsungkan semua serba spontan. Saya tidak biasa untuk membuat daftar kerja. Bahkan untuk menulis karangan saja, tidak pernah melakukannya sesuai kaidah. Saya menulis nyaris tanpa alur yang sudah konkret. Jadi saya selalu menulis dengan pikiran kosong. Yang kemudian baru mendapatkan ide saat saya menulis. Ini bisa dilihat dari karangan cerita yang saya tulis. Seolah ceritanya miliki paralel yang berbeda, saling menindih, dan jarang memiliki akhiran. Namun saya pikir ini adalah karya menarik karena organik. Dan saya baru tahu bahwa metode menulis seperti ini pun dilakukan oleh Haruki Murakami. Dan sama seperti menulis lagu. Biasanya nada dan liriknya saya dapat secara spontan. Malah inspirasi selalu didapat ketika saya tidak berniat untuk menulis lagu. Lirik-lirik yang saya tulis pun tidak pernah dipikirkan secara matang. Saya hanya menulis apa yang saya bayangkan. tidak pernah melakukan revisi. Semuanya dibiarkan murni.
Redaksi: Karya apa yang paling berkesan yang pernah dirimu buat dan mengapa memilih itu?
Fahriza: Novel Catatan Kobra! Ini menjadi kegiatan menulis paling lama dan panjang untuk pertama kalinya yang saya lakukan. Belum lagi, cerita saat proses menulis pun sangat berkesan. Saat itu kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Ya, akibat pergaulan blues. Hahaha. Saya menjalani semacam masa rehabilitasi atau pemulihan mandiri. Kondisi kesehatan saya baik fisik maupun mental sangat berantakan. Saya berpikir bahwa sebentar lagi mungkin saya akan mati. Dan pikiran itu selalu menghantui saya setiap waktu. Saya mulai mencoba menulis tentang masa-masa indah saya pada zaman sekolah dasar. Alasannya, agar bila saya mati saya bisa dikenang oleh sahabat-sahabat saya. Dan sebagai bentuk syukur bahwa saya pun pernah merasakan momen-momen hangat dan bahagia.
Novel Catatan Kobra saya rilis secara mandiri. Versi E-book bisa diunduh secara gratis. Dan lewat karya ini teman-teman saya yang diawal tidak tertarik membaca, jadi malah tertarik. Tak sedikit yang kemudian meminta saya untuk memberikan rekomendasi bacaan. Dan lewat Catatan Kobra saya bisa dipertemukan dengan orang-orang baru yang berkecimpung di ranah kesusastraan. Dan mendapatkan pekerjaan menjadi seorang penulis di media lokal hingga lembaga swadaya masyarakat.
Redaksi: Tema-tema apa sebenarnya yang sering dirimu angkat dalam berkarya, baik sastra maupun musik, dan mengapa memilih fenomena itu?
Fahriza: Cinta! Hahaha! Secara garis besar objek yang saya mainkan dalam karya saya itu tentang cinta. Namun di dalamnya terkandung irisan budaya dan sejarah.
Redaksi: Bagaimana dirimu melihat perkembangan karya yang telah rampung dibuat dari waktu ke waktu? Misalnya tentang perubahan gaya, tema, dan teknik?
Fahriza: Ini jadi hiburan tersendiri untuk saya. Menyimak karya-karya lama membikin saya merasa geli sekaligus kagum. Geli ketika mendapati karya lebay yang membikin saya cekikikan dan ingin menggigit tangan saya sendiri. Dan kagum ketika mendapati karya lama yang baru bisa saya nikmati dan menimbulkan pertanyaan untuk saya, “Kok dulu gue kepikiran ya bikin kaya begini? Kenapa sekarang gak bisa?”
Redaksi: Apakah ada pesan khusus yang ingin dirimu sampaikan melalui karya-karyamu yang telah rampung baik di dalam karya sastra dan album lagumu?
Fahriza: Tentu saja. Akan tetapi saya tidak pernah memberi perhatian secara gamblang terkait pesan di dalam karya-karya tersebut. Saya hanya memberi petunjuk saja. Selebihnya saya serahkan kepada penikmat untuk merangkum apa pesan tersebut.
Redaksi: Bagaimana menurut dirimu komunitas sastra dan musik di Bogor saat ini? Maksudnya, tentang kelebihan, kekurangan, atau bahkan mengenai potensinya.
Fahriza: Hmm… menurut saya komunitas tidak akan bergerak ke mana-mana jika kita tidak sama-sama membangun sarana dan prasarana. Selama ini yang saya tinjau kita sibuk membuat sarana. Sedangkan prasarana kita abaikan. Sejak dulu banyak sekali komunitas sastra dan musik. Namun segmen mereka hanya berputar di situ-situ saja. Pada akhirnya mereka capek sendiri dan hilang. Untuk musik, sejauh ini komunitasnya memang terbilang tetap hidup. Namun seperti yang bisa kita lihat semuanya saling terpisah. Sehingga menimbulkan banyak asumsi-asumsi kerdil yang saling meremehkan. Intinya, yang saya amati komunitas di Bogor hanyalah ajang untuk berkompetisi. Mereka terlihat bukan ingin memajukan kotanya. Melainkan hanya untuk mencari pengakuan siapa yang lebih dulu dan lebih keren. Itu di musik sih. Kalau sastra, sejauh ini belum ada tanggapan. Haha.
Redaksi: Apa peran komunitas dalam mendukung perkembangan proses kreatif dan karirmu? Dalam hal ini misalnya menyangkut jaringan, kolaborasi, dan dukungan.
Fahriza: Boleh dibilang saya tidak pernah tergabung dalam bagian komunitas, sih. Tapi saya miliki kedekatan dengan mereka. Biasanya kami saling bantu jika hendak mengadakan kegiatan. Namun saya juga kerap memilih komunitas. Saya orangnya skeptis dan idealis. Jika mereka miliki tujuan yang saya tidak sepakati, maka saya akan menjauh. Soalnya banyak kegiatan komunitas yang punya kepentingan sendiri yang berseberangan dengan prinsip saya. Tapi untuk jaringan pengkaryaan dan kolaborasi, kehadiran komunitas-komunitas kecil di bogor sangat membantu.
Redaksi: Bagaimana dirimu melihat prospek perkembangan seni secara luas di Bogor ke depannya?
Fahriza: Saya belum bisa membayangkan perkembangan seni di Bogor akan seperti apa. Hingga saat ini kita masih terbelenggu dalam khayalan. Entitas dasar saja belum terbangun. Kita hanya sibuk mengiblat ke kota-kota besar dan sibuk berkoar membandingkannya tanpa bisa berbuat banyak. Kita sibuk mengurusi komunitas masing-masing dan mengesampingkan cara agar bisa memboyong masyarakat tertarik untuk menikmati seni.
Redaksi: Kami penasaran, apakah ada tokoh atau komunitas seni di Bogor yang menginspirasi dirimu?
Fahriza: Memangnya Bogor punya tokoh, ya? hahaha.
Redaksi: Kami rasa, hmmm, hmmm, tidak ada juga sih memang, haha. Baiklah lupakan itu. Apa pendapat dirimu tentang perkembangan teknologi dalam dunia seni, khususnya sastra dan musik? Misal bagaimana pengaruh media sosial, platform digital, dan sebagainya.
Fahriza: Di era digital seperti dewasa ini, perkembangan teknologi memiliki peran yang terbilang vital. Kita bisa mengenalkan karya lebih luas dengan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Sejak awal saya belajar menulis saya menggunakan media digital sebagai tempat bersarangnya karya tulis saya. Sebut saja Blog. Dan karya musik saya, walau saya merilisnya dalam bentuk fisik. Akan tetapi bila saya lihat jumlah pendengar lebih banyak di platform digital.
Redaksi: Oke. Terima kasih atas waktu luang dan segala jawaban atas uraianmu, Mang. Terakhir deh, apa harapan dirimu mengenai para pegiat sastra dan musik di Bogor? Maksudnya, adakah harapan atau cita-citamu tentang lahirnya karya-karya monumental dan ekosistem yang berkesinambungan satu sama lain?
Fahriza: Mang, pertanyaannya susah euy. Saya ngantuk. Harapan saya semoga para pegiat sastra dan musik sadar akan tugas-tugas mereka untuk membangun ekosistem seni di kota Bogor. Walau kenyataannya memang sulit. Namun satu kunci agar semua itu mudah adalah dengan hati tulus dan ikhlas. Jangan terlalu mikir invoice diawal. Apresiasi seni tidak melulu soal nominal. Ditonton, dinikmati penuh hayat, dan membikin penonton terkesima sebab mendapat wawasan dan pengalaman baru saja sudah lebih dari bentuk apresiasi. Tapi, ya, itu tidak semudah menyantap potongan pesor dalam satu piring doclang. Duh, asli. Saya ngantuk, Mang. Jawaban saya jadi semakin melantur begini. Sebagai bakal calon wali kota Bogor, saya téh menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini. Dah lah. Saya mau bobo. Capek. Bye!