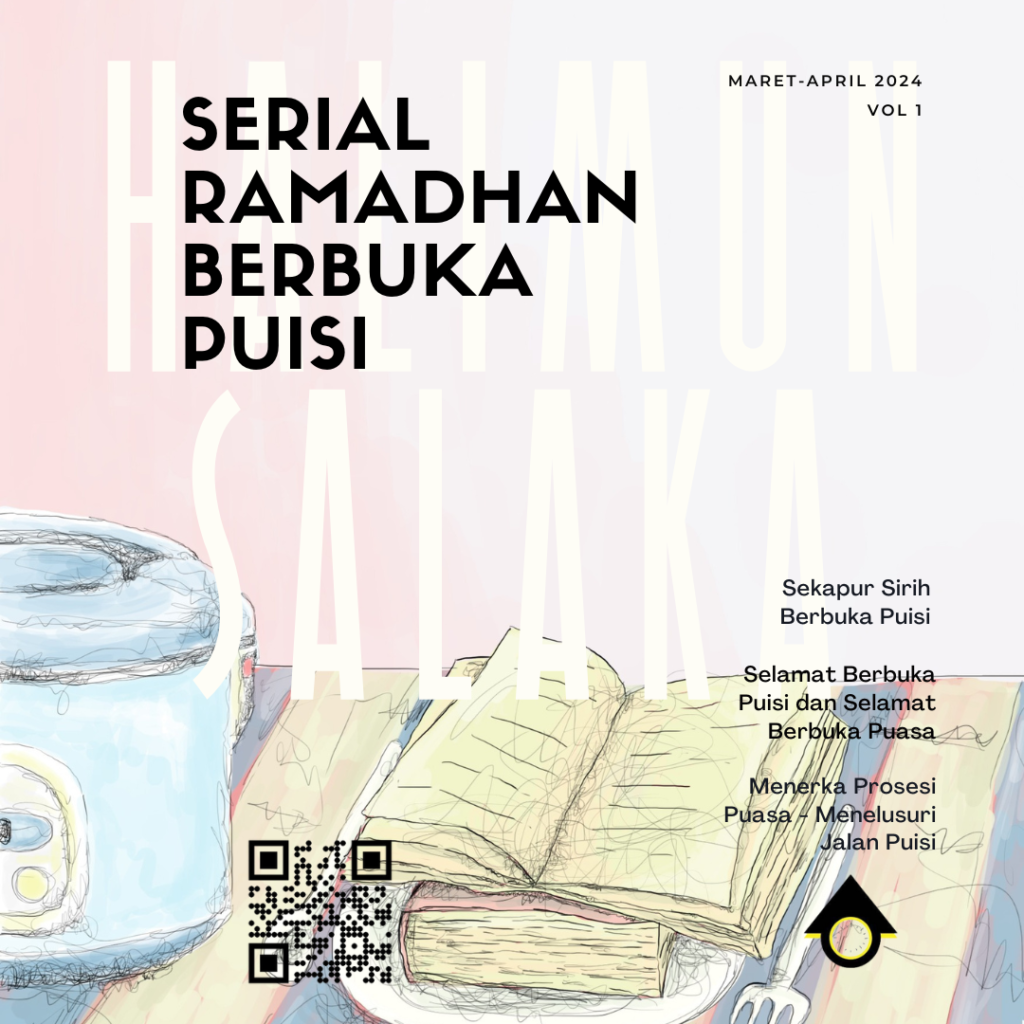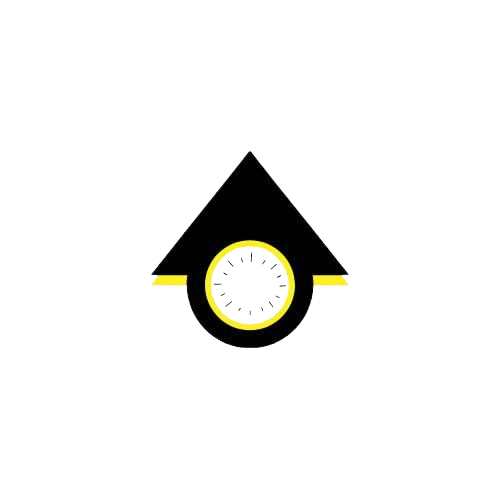ilustrasi @alanwari
Semudah apa kita bisa menemukan puisi? Mungkin pertanyaan retoris itu tak penting dan tak ada gunanya. Tapi, pertanyaan itu menjadi demikian karena kita secara tak sadar sudah memahami jawabannya. Terlalu seringnya kita menemukan puisi, misalnya, menjadi salah satu jawaban. Atau barangkali, kita tak pernah menyadari betapa bertebarannya puisi di sekitaran kita yang akhirnya membentuk jawaban itu sendiri. Begitu mudahnya kita menemukan puisi di zaman sekarang, di pelbagai media seperti buku dan terutama media-digital menjadi faktor betapa puisi bukan lagi hal aneh dalam kehidupan sehari-hari bagi siapa pun. Hal itu sama seperti, sering kali kita sadar dan kadang tak pernah menyadari bahwa kita berkedip-bernafas dengan mudahnya. Mungkin puisi hari ini serupa kesadaran dan ketidaksadaran serupa itu.
Puisi juga, saat ini menjadi media yang sering digunakan orang untuk dengan mudahnya mencurahkan isi hati dan perasaannya. Misalkan saja ketika dia merasakan kegundahan atau bahkan kebahagiaan. Perasaan-perasaan itu tumpah bersama pengalaman dan pengetahuannya sendiri terhadap puisi. Mereka menggunakan ketidakbiasaannya dalam berbahasa dalam puisi. Menumpahkan segala yang ada di kepalanya dari hasil membaca dan mengamati. Juga tak jarang, diksi-diksi yang keluar bisa menjadi indikator pengaruh bacaan-bacaan yang dikonsumsi seseorang.
Dalam melihat dan melakukan pembacaan puisi-puisi yang masuk ke meja redaksi Halimunsalaka.com akhir-akhir ini di masa #selamatberbukapuisi, tentu kami menemukan banyak hal-hal menarik. Termasuk bagaimana seseorang mendefinisikan Puisi dan Puasa di bulan Ramadan, kemudian menumpah-ruahkannya menjadi bentuk yang diyakininya. Redaksi sungguh menampung pelbagai karakter puisi dan dengan rendah hati tak melakukan kurasi yang signifikan. Walau dalam kenyataannya, kami sering beradu-argumen terkait puisi-puisi yang masuk.
Redaksi jelas, tak ingin membatasi karya puisi pada kemampuan dan pengetahuan kami tentang puisi. Kami begitu saja memberikan ruang yang luas bagi siapa pun, dari kalangan apa pun untuk berkarya. Mungkin, di serial ini salah satu karya di antara mereka ada yang merupakan karya pertama yang dipublikasikan, atau minimal yang masih terlihat malu-malu dalam menulis. Kami mungkin terlihat naif atau berusaha bermain-main dengan puisi. Tapi sungguh, kami ingin puisi mendapat tempat yang pas dan luas di hati siapa pun baik bagi penulisnya maupun bagi pembacanya.
Puisi dan Puasa: Soal-soal Kerinduan
Seperti halnya bahwa puisi juga termasuk karya yang lahir dari menembus batas penggunaan bahasa dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman, kami pun ingin kita mengilhami bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang menuntut kita melakukan aktivitas berbeda dari kebiasaan sehari-hari, bahkan bisa saja melampauinya. Yang biasanya tidak bangun dini hari, harus bangun dini hari; yang biasanya ngopi pagi hari, harus meninggalkannya; yang biasanya tidak berkumpul ketika magrib tiba, kemudian kita melakukannya. Hal-hal itu sama seperti puisi. Yang biasanya kita menggunakan bahasa secara lugas dan tegas, kita sembunyikan; biasanya kita tak peduli pada keindahan bahasa, tiba-tiba kita harus memikirkannya, dan seterusnya. Maka, Puisi dan Puasa adalah hal yang secara konseptual, mungkin ingin kita menembus kebiasaan kita, melampaui apa yang tidak kita sukai, tidak kita mengerti, dan seterusnya, agar belajar daripada prosesinya.
Seperti pada puisi Hari-hari Memasuki Ramadan karya Moh. Aldy Almahfudzi. Apa yang dirasakan orang-orang ketika memasuki bulan Ramadan begitu tampak jelas. Namun, bukanlah kebiasaan rasa rindu karena gembira dan kemeriahan dalam penyambutannya. Aldy malah menyoroti persoalan sosial yang kadang ada orang yang “terperangah” menyambut Ramadan. …ini terjadi menjelang Ramadan/suatu pagi, suatu rumah/ketika iklan di televisi menggeledah//mainan baru, Kekuasaan//…//Siapakah mereka?/ Siapa/ yang menyambut Ramadan penuh suka/ sedang menatap daftar harganya serupa surat duka//…. Aldy begitu cemooh kepada orang yang menyambut suka Ramadan-nya, namun tidak dengan kebiasaan ekonomi di dalamnya. Aldy secara cerdik menelisik di balik kegembiraan itu, masih ada dan mungkin banyak orang yang (kurang mampu, misalnya) tengah mengeluh karena harga bahan pokok naik, seperti langganan kebiasaan ketika memasuki Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Berangkat dari sana, puisi Bulan yang Berpuasa karya Teguh Tri Fauzi malah merefleksikan sudut pandang dan ide reflektif yang lain, ketika ia berdoa …Aku meminta, sebagai hamba-Mu/ di bulan puasa ini/ pertemukanlah anak-anak yatim-piatu dengan orang-tuanya/ walau hanya di dalam mimpinya/ walau hanya beberapa saat saja… yang dengan tegas memantulkan cermin keadaan bahwa, walaupun di bulan puasa/ramadan ini lumrahnya kita bahagia serta bersyukur dipertemukan dengan bulan yang suci, ternyata masih ada pula kesedihan, terkhusus anak yatim-piatu yang merindukan orang tuanya. Dan kita tahu, yang dirindukan anak yatim-piatu apalagi ketika sampai pada gema takbir dan hari lebaran, adalah pelukan kasih-sayang orang-tuanya, sebagaimana dilukiskan oleh Teguh, …sungguh/ ketika malam terawih gema doa-doa kumandang/ Ya Allah/ ketika pelukan menyatu pada lingkaran kasih-sayang/ di ruang kerinduan anak yatim-piatu itu/ air mata serupa hujan-kabut di pegunungan/ dingin dan sunyi/ menusuk sela-sela lorong hati… orang yang melihat dan merasakan kesedihan atas rindunya.
Menariknya, Sitti Fattimah lalu mempertanyakan tentang sebenarnya Ramadan Milik Siapa?. Kenyataan bahwa Ramadan bisa menjadi refleksi diri benar-benar dimanfaatkan oleh perenungan Fattimah. Dengan pengamatannya pada kemegahan dan kemamapan kota, nilai kehidupan kota yang seperti apa, yang bisa menyelamatkan seorang anak kecil serta ibu yang kesusahan? Bagi anak kecil dan sang ibu (yang menggelandang di jalan), mungkin puasa adalah bukan hal baru, dan tak akan pernah berubah maknanya. Tapi, keberkahan menjelang berbuka dengan banyaknya orang yang berbagi di jalan-jalan tempat tinggalnya mungkin jadi hal yang dirindukan mereka. Kegembiraan itu digambarkan sejalan dengan kepedihan seorang narator puisi yang menyaksikan kegembiraan itu. …/sampai akhirnya tiba, sebuah kotak berwarna putih/ yang diberikan seseorang/ raut wajah sang anak amat bahagia/ sembari menari-nari bersama kotak putih//…//sedang di depannya, seorang ibu memandanginya/ dengan penuh haru,/…//tidak ada seorang anak yang kuat/ jika setiap hari harus berpuasa, tanpa sahur/ tidak ada seorang ibu, yang senang anaknya berpuasa/ tanpa menyediakan menu untuk berbuka//…. Siti Fatimah juga seakan mempertanyakan: apakah mereka merindukan Ramadan yang mungkin bukan miliknya?
Sungguh miris kenyataan yang digambarkan puisi-puisi tersebut tentang lika-liku sikologi-sosial di balik kemeriahan Ramadan dan puasa. Hal tersebut juga digambarkan oleh Deden Fahmi Fadilah dalam puisi Munggah, yang menceritakan bagaimana tokoh seorang Nenek yang dicekam rindu tak tertahan menyangkut riungan keluarganya, terkhusus suami tercintanya, Nenek yang sebatangkara itu bertanya, …Apakah munggahan tidak boleh dilakukan oleh orang sebatang kara?// Dirinya mulai bertanya pada bayangan sendiri/ di sebuah cermin retak yang tertempel di sebuah lemari peninggalan mendiang suaminya// Dia membuka lemari itu dan memilih-milih mukena putih-polos yang cuma satu-satunya… itu menyebabkan kemelut suasana kita sebagai pembaca akan menempuh kesunyian kita masing-masing, bagaimana jika si Nenek tua itu merupakan Nenek kita sendiri? Atau keluarga dekat kita sendiri?
Dan oleh Egi Abdul Mugni dalam puisi Puasa Para Perantau diperjelas dengan sudut pandang lain, Egi mengubah tokohnya menjadi seorang anak muda yang sama dalam studi-kasusnya: dilanda badai kerinduan tak betepi menyangkut nuansa ramadan yang tak seperti dahulu. Sejatinya, ada kerinduan yang terpancar dari sudut puisi Munggah dan Puasa Para Perantau, yaitu tentang bagaimana gambaran puasa dan Ramadan membawa puncak kerinduannya masing-masing, yang biasanya digambarkan penuh dengan kehangatan keluarga, ….//Ma. tiada rasa puasa ini,/tidak ada lagi menunggu azan bersama/tiada juga menikmati lagi masakanmu, Ma//…. Sekali lagi, kadang Ramadan menjadi momen yang tak biasa bagi orang-orang dengan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki Ramadan itu sendiri.
Masih banyak tentunya penulis yang merefleksikan kerinduan hal lain di bulan puasa. Seperti yang mungkin pengalaman tertentu yang sangat ingin diulanginya sebab menurut Zhulian, Ramadan selalu membawa Halu yang Tak Kunjung Bertemu. Bagi Zhulian, puasa yang sedemikian menahan nafsu, lapar, dan dahaga merupakan umpama-umpama yang pas baginya untuk menahan rindu. Karena baginya, pertemuan mungkin sebuah momen “berbuka puasa” yang diinginkannya namun sulit dilakukannya ….//tapi di mana sop buah itu berada, Kekasih?/apakah ia sudah habis ditelan jiwa yang tak lagi berpuasa?//… .Entah apa yang terjadi pada “Kekasih” menurut si Aku. Mungkin maksud dari jiwa yang tak lagi berpuasa adalah seseorang yang telah “menghalalkan” sang Kekasih? Begitu perih jika itu, benar. Namun, yang pasti, dari puisinya kita bisa melihat bahwa puasa kali ini bukan lagi tentang dirinya ….//ah sudahlah/setiap puasa memiliki cerita/meski kali ini tidak lagi dengan dirinya.
Kemudian, si aku yang jelas kesepian pada puisi Zhulian tadi, juga digambarkan oleh Muhamad Fajar Muttakin pada puisinya yang berjudul: Kotak Nasi. Jika tadi kotak nasi menjadi simbol kegembiraan anak miskin, pada puisi ini, justru kotak nasi menjadi simbol kepedihan si aku. Bayangkan, Fajar secara cerdik meuliskan gambaran orang berbuka puasa dengan kotak nasi yang telah tersedia–tidak perlu menunggu pemberian orang, namun di dalamnya tak bisa memuaskan lapar-dahaga rindunya. Kotak nasi menjelang magrib bertumpuk/ “ini untuk orang-orang kesepian”, katanya/ Cita rasanya terlampau jauh dari rumah/ Jika ada rasa yang sama,/ sudah dipastikan rindu tertelungkup di antara lauk pauk. Belum juga dibuka, sudah digambarkan bahwa berbuka puasa bukan hanya soal cita rasa, tapi juga mungkin soal cinta rasa yang disimbolkan lewat kata “rumah”. Jelas momen Ramadan digambarkan bukan soal puasa dan buka puasa, tapi juga hal-hal di luar itu, lihatlah bagaimana mana tercipta momen puitika dari wahana puasa dan berbuka, …//Kotak nasi berisi sepi/di luar kotak lebih sunyi/duduk bersila sendiri/di depan kotak nasi/yang berisi sepi.
Sejalan dengan itu, persoalan puasa dan puisi yang menghasilkan momen puitika dihadirkan pula oleh puisi Ilham Alfarizy, berjudul Bukankah. Kecerdikan Ilham terlihat ketika ia melihat angin dan hujan sebagai modal penghayatan untuk menyampaikan kerinduannya, …Hujan yang jatuh malam ini/ begitu menggigilkan hingga ke tulang/ Kutitipkan puisi ini pada angin/ yang bersautan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an// Lalu kudapati makna pencerahan:// Puasa melawan nafsu/ Puisi melawan rindu/ Keduanya sama-sama melawan:// yang satu melawan lapar/ yang satunya melawan debar… dan lalu disambut apik oleh Teguh Syafaat dalam puisi Ayat-ayat yang Belum Lenyap, Mengingatmu adalah ziarah panjang dari azan ke azan; dari sahur hingga berbuka; dari subuh sampai magrib tiba… Dan ketika magrib dan berbuka tiba, Ragil Sauri ikut menambahlan dalam puisinya berjudul Pertumbuhan Puisi di Atas Meja Makan, …Di waktu yang hampir bersamaan/ Puisi baru saja dimulai/ dalam menu makan malam… yang mana ketiga puisi itu sangat berkait-kelindan prosesi ide pengkaryaannya.
Setelah nuansa, ide, penghayatan di dalam dan di luar kerinduan puasa dan puisi itu, semuanya akan sampai pada pertanyaan yang sama, sebagaimana Luthfi K Umam dalam puisi Pulang menabur pertanyaannya, …Jika langkah kaki ini sudah terlalu jauh melangkah/ dari arah jalan pulang/ maka kemana aku akan pulang?// Jika kematian adalah sebuah kepastian/ untuk menuju jalan pulang,/ apakah setelah kematian aku akan kembali/ mencari arah jalan pulang?… Umam membawa kita pada serangkaian perjalanan panjang labirin hidup menuju kepastian atas kematian, kematian menuju kehidupan yang abadi, yang mana puncak dari segala puncak kerinduan manusia mungkin sangat tepat jika kembali pada ke-ilahi-an Tuhan.
Puisi dan Puasa: Soal-soal Ketakwaan
Jika tadi kita berbicara bahwa Ramadan dari sudut perubahaan kebiasaan sosial dan perasaan yang terlibat di sana, lebih khusus nuansa kerinduan. Maka, kita juga patut meninjau bersama juga bahwa Ramadan merupakan momen yang pas untuk mengubah kebiasaan ketakwaan. Tentu saja, bukan menjadi lebih buruk. Momen ini mesti dimafhumi sebagai tonggak mula perubahan spiritualitas. Juga, dengan harapan bahwa perubahan itu merupakan terobosan dari kemalasan-spiritualitas kita dan berlanjut hari-hari setelah puasa berakhir. Tidak ada satu orang pun yang bisa menilai ketakwaan orang lain, bahkan nilai ketakwaan dirinya. Begitu pun soal peningkatannya dalam momen baik seperti Ramadan ini. Kita tidak tahu pula, proses tahapan nilai berapa kita bermula untuk meningkatkannya di bulan Ramadan ini.
Seperti yang diuraikan puisi dari Shankara Araknahs yang berjudul Sisifus Nyoba Puisi. Dari judulnya saja kita sudah diperkenalkan dengan sosok dewa(?) dari mitologi Yunani. Jelas bahwa itu memang sama sekali tidak bernuansa Islami. Namun bisa kita lihat bahwa Sisifus merupakan sosok yang juga berpuasa atas kemelut hidupnya, walaupun jelas tidak memahami puasa dalam metode Islam. Mungkin, Shankara ingin mengkritik secara epik dengan menggambarkan bagaimana proses orang-orang yang puasa, kadang-kadang sebagian dari kita manusia mungkin hanya menahan nafsu badaniah saja, tanpa memperhatikan nilai rohanian, dan itu tergambar oleh Shankara dalam puisinya dengan meminjam tragedi Sisifus sebagai “tumbal kreatifnya”.
Sisifus, seperti yang kita tahu, adalah sosok yang dihukum untuk menggelindingkan batu besar ke atas bukit atau gunung dari akibatnya berulah sampai memalsukan kematiannya di depan dewa kematian dan neraka. Intinya, sosok Sisifus ini merupakan sosok yang buruk di dalam ceritanya. Ketika dipinjam oleh penulis untuk menjadi sosok yang sangat bepuasa setiap harinya selama menjalani hukuman, tentu baginya suatu kebebasan–dari hukuman. Penulis ingin menggambarkan bahwa “siksa” menahan lapar, haus, dan nafsu di bulan Ramadan merupakan suatu bentuk “penebusan dosa” untuk kita kembali pada masa suci kita dan fitrah. …//bibi pecah-pecah pusing di kepala keringat yang berlebihan/dehidrasi dan lemas dari tulang sendi dalam perasaan baru bitu, dengan sedikit tersenyum ia bertanya pada kecemasan://”O, mungkinkah ini yang namanya kebebasan?”.
Setelah itu, Fahriza Nugraha malah menawarkan hal baru tentang kenyataan spiritualitas orang-orang, yang di antara mereka mungkin banyak yang dengan serius beribadah, namun kenyataan dari Fahriza justru menjelaskan bahwa banyak juga yang “berpura-pura” atau mungkin dalam artian syariat, mereka beribadah namun sia-sia karena banyak hal yang dilupakan selain menahan lapar dan haus ketika berpuasa. Dalam puisi Amin, Fahriza menjelaskan sifat munafik yang mungkin ada dalam balutan yang dalam kasat-mata mereka adalah orang-orang suci. Bahkan dengan kasarnya Fahriza mengungkapnya dengan sebutan “mayat”(jasad manusia?) …//Namun mayat-mayatnya malah menjadi borok/ di hamparan sejadah. Kenyataan itu jelas pasti ada dan puisi ini patut menjadi pengingat bahwa, kita dalam beribadah apalagi di momen Ramadan itu harus ekstra berhati-hati, dan mudah-mudahan jauh dari kabut kemunafikan.
Persoalan itu diperjelas pula oleh Sah Agam, pada puisi berjudul Ibadah-ibadah Puasa, …kali ini kau lebih sering menjabarkan sajadahmu/ yang aromanya nyaris menyerupai barang-barang tua/ yang debu-debunya beterbangan menyebar dalam ruangan… dan si narator puisi menambahkan bahwa, …setiap waktu di bulan ramadan seperti musim bunga di taman/ lekaslah datangi guru agama/ tanyakan apapun yang ingin kautanyakan sebagai seorang pendosa. Sah Agam seperti meneruskan fenomena puisi Amin-nya Fahriza, meneruskan ketika tengah terjadi kemelut kemunafikan dalam diri yang penuh dosa, dianjurkan mengunjungi guru agama: sebagai orang yang memiliki pengetahuan di atas kita, meminta kisi-kisi menempuh jalan aman dunia.
Wahana pembayangan ketakwaan yang berbeda dari kedua puisi di atas sebelumnya, menariknya diperlihatkan oleh Imam Budiman pada puisi berjudul, Puasa Hari Pertama di Mars. Imam cerdik mengolah ide puasa dan puisi melalui pantulan pembayangan bagaimana kiranya kira hidup sehari dan menjalani puasa pertama di Mars? Pembayangan Imam membawa kita pada peristiwa, …Musim tak pernah ada di sini/ kemarau tak pernah menyentuh galaksi/ selain suaramu, suaramu// Tak pernah ada kiblat untuk kita pulang/ Barangkali berkebun di antara kawah dan batu/ menyemai bibit bintang/ ternak cahaya bulan/ sedikit menyembuhkan dari keterasingan… kita, mungkin tak akan mampu bertahan di sana, yang sudah pasti kita akan merindukan hidup di bumi dengan segala anugrah yang diberikan Tuhan. Seperti diuraikan pula dalam lanjutan puisinya, …Hanya suluh dan masa kecil/ serta sosok serupa alien/ menyertai satu niat untuk menjadi manusia seutuhnya.
Syahdan. Sekilas pembacaan puisi-puisi ini, yang mana memang sengaja kami niatkan agar tak utuh-menyeluruh. Setidaknya pembacaan kami di atas dapat menemani pembaca sekalian, terkhusus dalam menyusuri sekumpulan puisi-puisi yang ada di dalam Majalah kecil ini. Atau, paling tidak muatan pembacaan kami ini nama lain dari pintu ucapan terimakasih kami, karena bersedia berkunjung ke ruang pengkaryaan kami bersama dalam tajuk serial-ramadan #berbukapuisi. Dan sebagai penutup, disebabkan pembelajaran puasa sudah di ujung waktu akan berakhir, kita akan merefleksikan perjalanan berbuka puasa dan puisi ini dengan satu judul puisi terakhir di serial ramadhan, berjudul Malam Takbiran, olahan Syahruljud Maulana:
Mari kita pakai baju Tuhan:
utuh dan telanjang
Oh, inikah rasa manusia?
Selamat berpisah (untuk sementara) dengan puasa, dan selamat menikmati serta menepuh perjalanan panjang puisi seterusnya.***