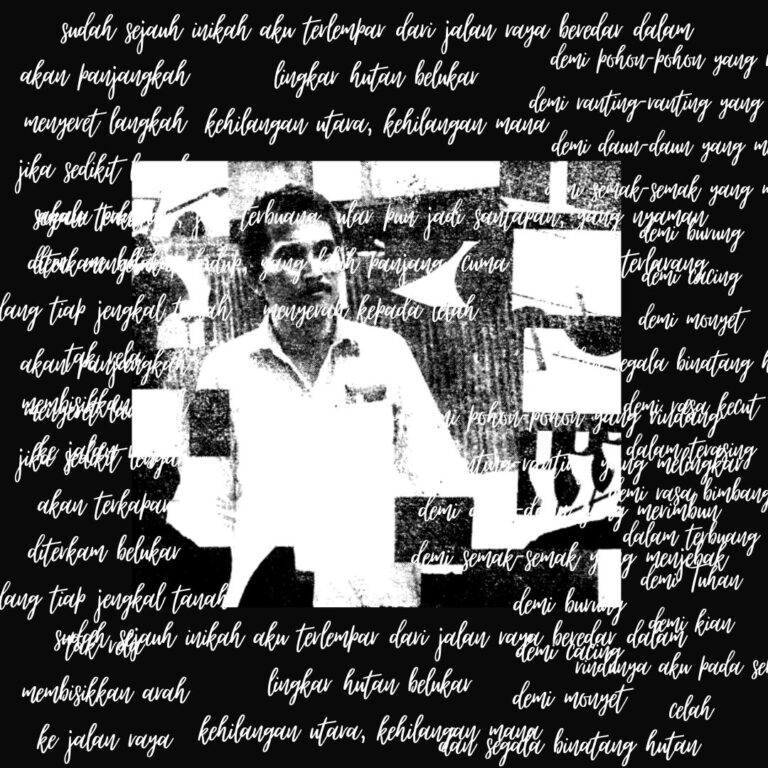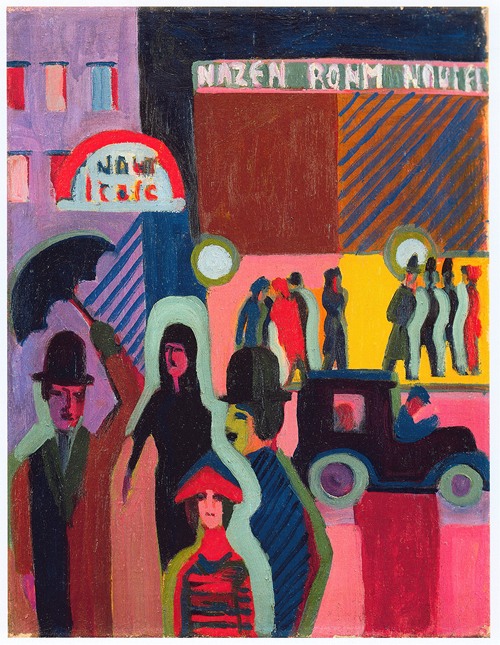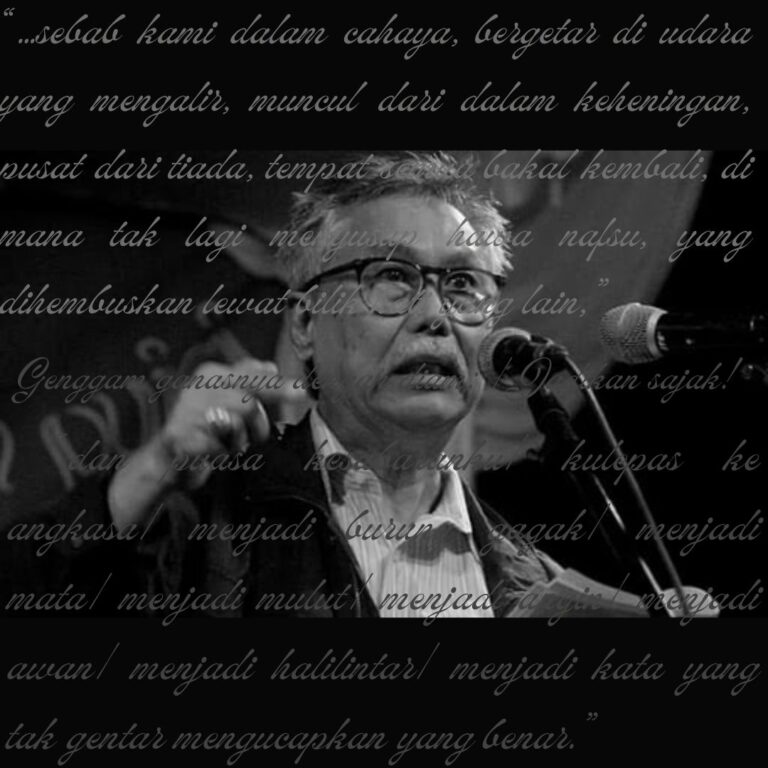Banyak orang mengenal hubungan politik dan diplomasi antara Kerajaan Sunda dan Majapahit, tetapi sedikit yang menyadari bahwa pusat kekuatan Sunda—Bogor—menyimpan kisah yang baru saja terungkap kembali ke permukaan—dengan mahkota kuno yang kembali ke tanah leluhurnya. Bayangkan suasana renyah lembah-lembah di Bogor pada abad ke-14, ketika Pakuan Pajajaran menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan Sunda. Namun, sebagian besar narasi sejarah sering melompati Bab Bogor, dan hanya fokus ke pusat politik Priangan dan Jawa Tengah dan Timur. Faktanya, Bogor bukan sekadar latar belakang—ia adalah juga wilayah penting yang kini baru sekali lagi muncul ke permukaan sebagai sorotan utama.
Kini, sebuah peristiwa pada tahun 2025 mengangkat kembali Bogor dari sejarah terpendam: Mahkota Binokasih Sanghyang Pake, hadiah bentuk legitimasi kekuasaan para raja Sunda, kembali untuk “singgah” di Kabupaten Bogor setelah berabad-abad berpindah tangan. Secara simbolis, ini seperti lampu sorot yang diarahkan kembali ke tempat lahir bagaimana drama politik dan budaya Jawa Barat. Pembaca tidak hanya diajak bertanya “siapa”, “untuk apa”, dan “kapan”—tetapi juga “mengapa baru sekarang?”
Kita tahu, Mahkota Binokasih bukan sekadar artefak, melainkan lambang nostalgia kolektif dan legitimasi tradisional yang selama ratusan tahun hilang dari pandangaan publik. Dibuat pada abad ke-14 oleh Prabu Bunisora Suradipati dari Kerajaan Galuh, mahkota ini terbuat dari emas murni seberat sekitar 8 kilogram, dihiasi giok lokal—lapisan kilau yang membawa pesan kekuatan budaya dan moral masa lalu ke masa kini.
Pada April 2025, mahkota ini dikirab ke Bogor melalui berbagai rangkaian acara—dari iringan seni wayang golek, talkshow hingga kirab rakyat—yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan penuh khidmat. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa ini bukan sekadar seremoni: ia adalah “momentum edukatif dan reflektif dalam memperkenalkan kembali jati-diri bangsa”. Di mana dulu mahkota itu hanyalah relik, sekarang ia menjadi pemantik identitas dan kebanggaan budaya.
Dalam sejarah Sunda–Jawa, kisah seperti Perang Bubat sering dikemas sebagai tragedi epik yang menyayat hati—romansa yang membara, cinta ditolak, dan kehormatan yang dipertaruhkan. Namun, sejumlah sejarawan meragukan validitas narasi ini. Menurut diskusi ilmiah dan para sejarawan di forum seperti Reddit, tidak ada prasasti dari era Majapahit atau Sunda yang menyebut Perang Bubat—bahkan Negarakertagama, karya kontemporer utama, sama sekali tidak menulis tentang kejadian itu Reddit. Artinya, narasi yang diwariskan sebagian besar berasal dari naskah seperti Kidung Sunda atau Pararaton, yang biasanya muncul ratusan tahun kemudian—hingga bisa dipandang sebagai sekilas legenda ketimbang sejarah solid.
Contrast that dengan keberadaan fisik Mahkota Binokasih—artefak nyata, berkilau, dan kini kembali ke Bogor—yang mengkontraskan mitos yang tak terverifikasi dengan realitas yang bisa disentuh dan dilihat. Ini semacam pengingat: sejarah yang otentik tak selalu berupa kisah dramatis lalu mitologis—kadang cukup seporsi emas dan giok, kalau memang benar ada.
Sekarang kita beranjak ke makna. Kembalinya mahkota ini bukan hanya soal nostalgia, tetapi menyulut semangat baru —seperti semboyan “Bumi Tegar Beriman” dan “Kuta Udaya Wangsa” yang digaungkan Bupati Bogor selama kirab. Filosofi yang diusung: kepemimpinan harus welas asih, inklusif, dan berdiri tegak bersama rakyat—nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur dan kembali relevan di era modern.
Acara kirab ini juga membawa budaya ke ruang modernitas—dengan talkshow, wayang, dan pendalaman nilai-nilai kepemimpinan untuk generasi muda. Mahkota menjadi simbol hidup, bukan hanya benda antik; di dalamnya tertanam identitas, tanggung jawab, dan harapan akan masa depan Sunda yang harmonis.
Dari sejarah mitos ke artefak nyata, dari narasi yang diragukan ke bukti yang bisa dilihat—kita diajak bertanya: Apakah kita hanya mau terjebak dalam legenda yang mungkin dibuat-buat, atau mulai mencari artefak nyata yang menguatkan identitas kita? Mahkota Binokasih hanya salah satu di antara banyak warisan yang mungkin tersimpan rapi di museum atau cagar budaya. Dan hal itu mesti menjadi wahana kritis kita dalam mempertanyakan dan mempertimbangkan kembali apa makna masa lalu dan apa guna masa depan.
Mari kita gunakan momentum ini untuk menumbuhkan keingintahuan kritis—bukan sekadar menerima narasi penuh drama, tetapi menggali terus-jejak sejarah dengan dan bahkan radikal-bijak. Siapa tahu, di balik bayang-bayang legenda, ada artefak lain yang menunggu untuk menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa depan Sunda–Jawa, lewat semangat kepemimpinan bersama dan cinta tanah air yang lebih cerdas, arif memaknainya.