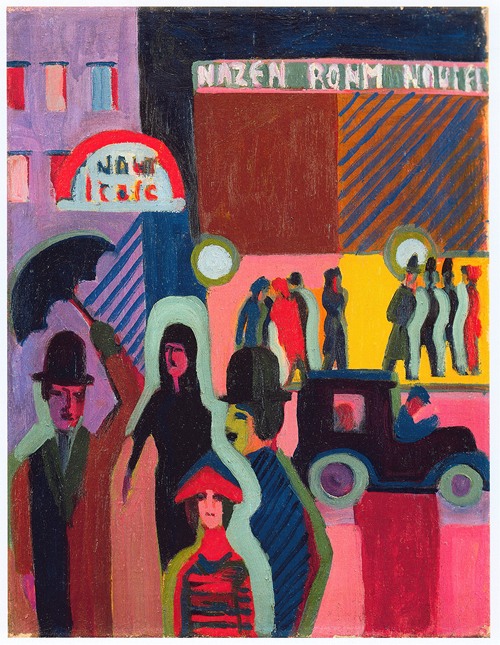Dia yang berjalan mengembarai kehidupan. Adalah dia yang sepanjang hidupnya menjelajahi dunia hina dina, hanya untuk sekedar menertawakannya, karena dia telah menempuh semua perjalanan. Dia berjalan dengan kaki kesejatian. Dia berjalan dengan tangan kemerdekaan. Dia berjalan dengan kepala kesadaran. Tetapi ternyata, dia lebih banyak berjalan melalui lintasan-lintasan pikirannya.
Dia meladeni derita dunia. Memberi suara pada apa yang tak kedengaran lagi. Segala luka yang kemarin dari suatu masa, konstelasi, lingkungan, kebudayaan, zaman, peradaban—dibawakannya ke hari ini sebagai batu uji pikiranku. Dia mewariskan ilmu-ilmu, kritik sosial, dan pergaulan hidup yang bersahaja. Dia lelaki dari penghuni jiwa sejati. Dia kekasih lingkungan hidup yang wajar. Dia pengelana di rimba kejernihan kalbu. Dia penyair flamboyan yang mendapatkan gelar sebagai “Panglima Puisi”. Aku bukan.
Dia adalah Husni Djamaluddin, yang hidup dan kehidupannya, aku menyangka dan mengenalinya masih sebatas penyair—yang malam kemarin kembali diketahui, ditelisik, dipahami, dimengerti, dimaknai, dihayati, dan dibahas dalam majelis Semaan Puisi episode 97. Aku belum pernah berjumpa dengannya, tetapi namanya tidak asing dalam alam perpuisianku. Sejak lama perkenalanku bermula dari membaca tatapan sajak-sajaknya, dari mendengar tuturan Simbah Nun (Emha Ainun Nadjib adalah sahabatnya Husni Djamaluddin) pada suatu maiyahan.
Sesungguhnya aku tidak tahu apa-apa tentang Husni Djamaluddin, selain lewat bentangan sajak-sajaknya. Aku tidak mengalami hidup secara langsung menyaksikan penderitaan kayak apa yang selalu dia layani. Tetapi puisi yang bersemayam dalam diri sepanjang hidupnya, seolah-olah berbicara kepadaku bahwa penderitaan tak pernah bisa membuatnya menderita, karena dia selalu merasa ada yang jauh lebih menderita daripadanya. Maka lewat sajak, dia menyapa hati yang ditubir penderitaan, menemani jiwa yang gelisah bertalu-talu, dan mendengarkan pedih pilu nyanyian alam yang merintih.
Di sini aku cuma mengintip sekilas ke dalam ruang kehidupan jiwa Husni Djamaluddin yang sesungguhnya. Dia melalui sapaan sajaknya yang lantang mencampakkanku ke ruang kesejatian. Ruang di mana dia pernah merespons ilusi dunia sungsang, dekadensi zaman, dan darurat iklim yang kian hari makin tak tertolong lagi. Ruang di mana dia sempat mengayomi sekaligus mengasuh anak-anak muda tanggung, yang pergaulan hidupnya liar, dan suka mabuk-mabukkan itu, diarahkannya ke jalan kreatif berkesenian. Ruang di mana dia senantiasa meladeni segala bentuk penjajahan, kebudayaan disko, serta polah tingkah menghambur-hamburkan seluruh usia berpusing-pusing dalam kecetekan, kecekakan, dan kedangkalan hidup. Ruang di mana dia selalu mengamati gerak gelisah dengan mata sejati dan mata abadi. Ruang di mana dia menangkap tragedi kalau dari dekat, dan komedi kalau dari jauh. Seperti sajak “Pada Mulanya Sepi”:
Tuhan
sepi
Tuhan tak mau sepi
adam jadi
adam sepi
adam tak mau sepi
eva tiba
kau sepi
kau tak mau sepi
aku ada
aku sepi
aku tak mau sepi
kau ada
jadi dari sepi
tiba dari sepi
ada dari sepi
ada dalam sepi
kau dan aku
bertemu
membagi sepi
sepi tak bertemu
sepi tak terbagi
sepi tak bertepi
sepi yang sunyi
sepi yang asasi
sepi yang kau
sepi yang aku
sepi nya kau
sepi nya aku
k a u
k a u
a k u
aku
Serius. Husni Djamaluddin itu seorang penjelajah estetika yang ulung. Banyak bentuk telah dia coba. Tak satupun “bentuk” sanggup memenjarakannya. Bahkan, penyelidikannya atas segala irama sajak: metrik, metrum, rima, ritme, matra, dan apapun itu tak mampu menguasai kepenyairannya. Dia piawai dalam menggagahi segala bentuk, juga sangat lihai dalam mengatasi beragam gaya ungkap maupun pola ucap. Semua bentuk dan semua suara telah diramunya ke dalam eksperimen persajakkan—yang entah mesti dengan apa kusebut ini? Karena tak kutemukan kata buat beliau.
Perhatikanlah puisi di atas. Apakah pembayanganmu langsung tertuju pada nama-nama seperti Sutardji Colzoum Bachri, Remy Sylado, Jeihan?
Dia bisa pakai gaya mantra, tapi puisinya tidak lantas jatuh ke Sutardji. Dia bisa coba pola mbeling, tapi puisinya tidak mudah terpeleset ke Remy. Dia bisa main-main kata, tapi puisinya tidak terjun bebas ke Jeihan. Seakan-akan dia menyindir penyair serius dengan mensintesakan temuannya masing-masing menjadi (semacam idiomatik) “mantra mbeling yang main-main”. Mengece penyair yang membela puisi mati-matian. Penyair tak tahu malu. Penyair tak ngerti diri. “Yang bangga jadi penyair,” kata Simbah Nun, “matilah sebelum mati.”
“Orang yang meletakkan kepenyairan di atas segala nilai hidup lebih baik ‘bunuh diri saja’,” celetukan Jeihan.
Mampus aku, tapi alhamdulillah hidupku penuh makna. Lagi pula kepenyairanku jauh panggang dari api, lebih jelasnya gagal total. Aku telah membunuhnya semenjak ingin jadi “apa”, lalu memilih berkeliaran “di mana-mana” sampai aku sendiri tahu berada “di mana”: kukerjakan dan kuhayati peran di dunia ini, seolah-olah seperti sungguh-sungguh aku hidup di dunia dan dengan dunia. Kemudian tibalah aku di puncak kebodohan. Ternyata puisi-puisi yang pernah kutulis itu hanya bikinan, dan bukan penciptaan. Apapun saja yang telah kutulis itu ternyata karangan, dan bukan kesejatian.
Aimak, Husni Djamaluddin seperti menampar mukaku. Karena aku terjebak dalam segala eksistensial remeh, tapi tak kunjung bangkit belajar dan memahami kesejatian hidup. Aku mengambil banyak kekeliruan dalam mengenalinya secara superfisial maupun artifisial melalui wujud-wujud temeh bahwa dia adalah penyair, eseis, penulis, dramawan, budayawan, tokoh, atau apapun. Dia yang mencampakkanku ke ruang kesejatian, tetapi karena persangkaanku terbatas pada gelagatnya, maka aku akan bisa kehilangan keutuhan dan keluasan Husni Djamaluddin.
Allah bukan sekedar Maha Besar, melainkan Allah Maha Yang Lebih Besar. Itu artinya manusia tidak boleh berhenti hanya menjadi manusia, kecuali ia tak bisa mengerahkan dirinya manusia. Demikianlah sebabnya pula manusia itu makhluk dinamis, makhluk kemungkinan. Jadi terserah-serah apa pemaknaan engkau atas puisi tadi. Mau dilihat dengan sungguh-sungguh atau keisengan belaka. Mau dimaknai dengan keluasan cakrawala berpikir atau disempitkan ke dalam moralistik yang kaku.
Puisi “Pada Mulanya Sepi” seperti menyiratkan tentang kebudayaan Lingga-Yoni, suatu simbolisasi yang merepresentasikan tipografinya sebagai proses kehidupan dengan segala penciptaannya. “Tuhan” berada pada larik pertama, sedang “aku” berada pada larik terakhir. Ini sepasang kata yang mewakili tentang penyatuan, nyawiji, dan manunggaling. Artinya, pada waktu sepi itu kenapa “Tuhan” menciptakan “aku”? Untuk apa “aku” diciptakan “Tuhan”? Aku ini anak-cucu yang sah keturunan Adam atau anak angkat iblis yang menyamar malaikat demi menghasut Adam? Kira-kira menurut engkau bentuk tipografinya lebih menyerupai “buah zakar” (titit) atau “pohon terbalik”? Sebelum sampai ke Adam, kira-kira mana yang lebih dulu kita pelajari: ilmu pohon atau ilmu iblis?
Begitulah Husni Djamaluddin mencipta dengan sejatinya, maqamnya, dan di tengah kosmosnya. Aku belumlah apa-apa. Belum sebatas Husni, apalagi mendekati. Kedua tanganku tak bisa menggapai di wilayah kesejatiannya. Mungkin karena aku sering mengalami apa kata sajak “Orang Tua” di bawah ini:
Orang tua mengajar anak-anaknya mulai bicara
Orang tua mengajar anak-anaknya pintar bicara
Orang tua mengajar anak-anaknya bicara benar
Orang tua bingung kalau anak-anaknya mulai bicara
Orang tua tersinggung kalau anaknya pintar bicara
Orang tua marah-marah kalau anak-anaknya bicara benar
Orang tua menganggap
anak-anak yang bicara benar
adalah anak-anak yang kurang ajar
Orang tua menyekap
anak-anak yang kurang ajar
di dalam kamar
yang pengapMenurut engkau lebih penting bertanya atau menjawab? Seharusnya kan pendidikan menjadi gelanggang untuk bertanya, bukan sekedar sarana menerima kunci jawaban. Hidup itu sendiri tentang bagaimana kita berani bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu—yang memang perlu dipertanyakan.
Sehingga pertanyaan penting buat hari ini: Siapa mau bertanya? Siapa yang peduli? Apakah masih ada perhatian kita terhadap suatu hal? Apakah kita benar-benar tidak pernah meragukan suatu hal tersebut? Bukankah pertanyaan itu sendiri adalah satu kecakapan penting yang perlu dilatih setiap hari jika engkau mau meningkatkan kualitas diri? Sama pentingnya dengan seni menulis puisi, atau workshop kertas daur ulang, atau segala bentuk aktivitas lainnya yang didalami oleh manusia.
Sekali engkau bertanya, niscaya tak akan pernah menemukan jawaban, kecuali hampir mendekati jawaban. Setiap pertanyaan yang mencari jawaban adalah jalan panjang menuju pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini jika engkau percaya bahwa hal yang lebih penting dari suatu pelajaran bukan tentang mendapatkan jawaban, melainkan keberanian dan kesiapan untuk senantiasa belajar bertanya. Sekali lagi ini jika engkau percaya bahwa hidup lebih banyak tidak tahunya, itu sebabnya engkau bertanya pada diri sendiri, menggali apa yang ingin engkau ketahui? Mendalami apa yang sebenarnya engkau inginkan? Menyelidiki sebab musabab kenapa engkau sampai bisa tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika melihat sesuatu? Masak tidak ada kemungkinan apapun yang bisa muncul dalam benak engkau agar terbiasa bertanya ketika mengalami-merasakan-menghayati sesuatu?
Hidup di zaman tsunami informasi begini, alangkah baiknya kita selalu belajar mewaspadai pikiran, sebab ia gampang dikacaukan, dibakar, dipengaruhi, dan juga diarahkan. Setiap hari media sosial kita lebih berisik mengatakan apa saja daripada yang sempat kita ucapkan dan kita percaya begitu saja. Kita akan menjadi santapan empuk yang ditelan oleh kebijakan-kebijakan penguasa yang lalim. Kita akan menjadi korban yang dipenjarakan buaian-buaian pikiran yang menipu. Kita akan lebih sering mengalami ketersesatan dalam kebingungan tak menentu yang ujung-ujungnya stress. Kita akan terseok-seok di tengah kepungan kicauan, sumpah serapah, caci maki, dan mungkin teriakan amarah membabi buta atau keluhan orang-orang dewasa yang putus asa.
Itulah mengapa pertanyaan begitu penting, sebab ia pintu masuk buat mengarahkan kesadaran. Ia mengarahkan kesadaran tentang diri sendiri sesuai perhatian yang engkau kehendaki. Pertanyaan merupakan hal yang harus dipelajari kembali kalau kita mau menggali informasi atau nyaris hampir menemukan jawaban. Sekelas Nabi saja selalu bertanya ketika dia menemukan Tuhan atau tengah mendapatkan wahyu. Masak engkau dan aku yang bukan Nabi ini tidak terbiasa bertanya kepada diri sendiri. Betapa kurang ajarnya kita karena memalukan ciptaan Allah berwujud manusia yang telah dianugerahi akal tetapi tak dipergunakan sewajar-wajarnya.
Aku agak menyesal karena tidak serius dan sungguh-sungguh mendalami seni bertanya. Terkadang aku bahkan takut bertanya, karena /orang tua menganggap/ anak-anak yang bicara benar/ adalah anak-anak yang kurang ajar/. Atau lebih tepat bunyinya, orang tua menganggap anak-anak yang suka bertanya adalah anak-anak yang cerewet, sok tahu. Baru sekarang aku menyadari betapa rindunya aku dengan bertanya. Seperti halnya sajak “Kemerdekaan Yang Aku Rindukan”, akupun rindu pada kesiapan diri untuk bertanya dan berani bilang tidak. Tidak ikut arus penanggapan yang berwatak pergibahan dan pergunjingan riuh yang selalu berlangsung di media sosial.
Di sinilah sajak-sajak Husni meneguhkan dirinya dalam berlaku, berprinsip, bersikap, dan selalu berdiri diposisi yang terjajah. Penjajahan itu bermacam-macam bentuknya. Maka dalam keterjajahan itu, dia menyangkal kesengsaraan dan menolak tunduk pada penyerahan. Tampaknya, kolonialisme merupakan bahan bakar khas yang “full tank“ disuarakan sajak-sajaknya demi menyerukan perlawanan dan memperjuangkan visi kemerdekaan yang sesungguhnya.
Kemerdekaan yang dia rindukan, bukanlah kemerdekaan kayak hidup yang kita alami dan jalani hari ini. Kemerdekaan yang dia rindukan, bukanlah mengisi kemerdekaan dengan perjumpaan-perjumpaan hina dan culas dalam politik kekuasaan. Kemerdekaan yang dia rindukan, bukanlah kemerdekaan yang diisi oleh perjumpaan-perjumpaan rakus serakah dalam berekonomi. Kemerdekaan yang dia rindukan, bukanlah kemerdekaan yang banyak dipenuhi oleh perjumpaan-perjumpaan palsu yang berdasar kepentingan segelintir orang atau segolongan. Kemerdekaan yang dia rindukan, bukanlah kemerdekaan yang sumpek oleh perjumpaan-perjumpaan takhayul dan mitos dalam berkebudayaan.
Jangan-jangan kemerdekaan yang dia rindukan, sesederhana memenuhi perjanjian cinta yang mendasar dan kenikmatan rindu pada kehidupan yang lebih manusiawi. Jangan-jangan kemerdekaan yang dia rindukan, seperti halnya anak-anak belajar bertanya, boleh bicara benar dan berani bilang tidak. Tunggu dulu, jangan-jangan kemerdekaan yang dia rindukan, adalah mengingatkan setiap orang itu bahwa jika kita ingin menemukan jawaban memuaskan dan meningkatkan kualitas diri terus-menerus, maka yang lebih penting bertanya kepada diri sendiri terlebih dahulu. Jangan-jangan kemerdekaan begitu yang dia, engkau, dan aku rindukan. Jangan-jangan, lho, ya.
Kebayoran Lama, 4 Oktober 2025