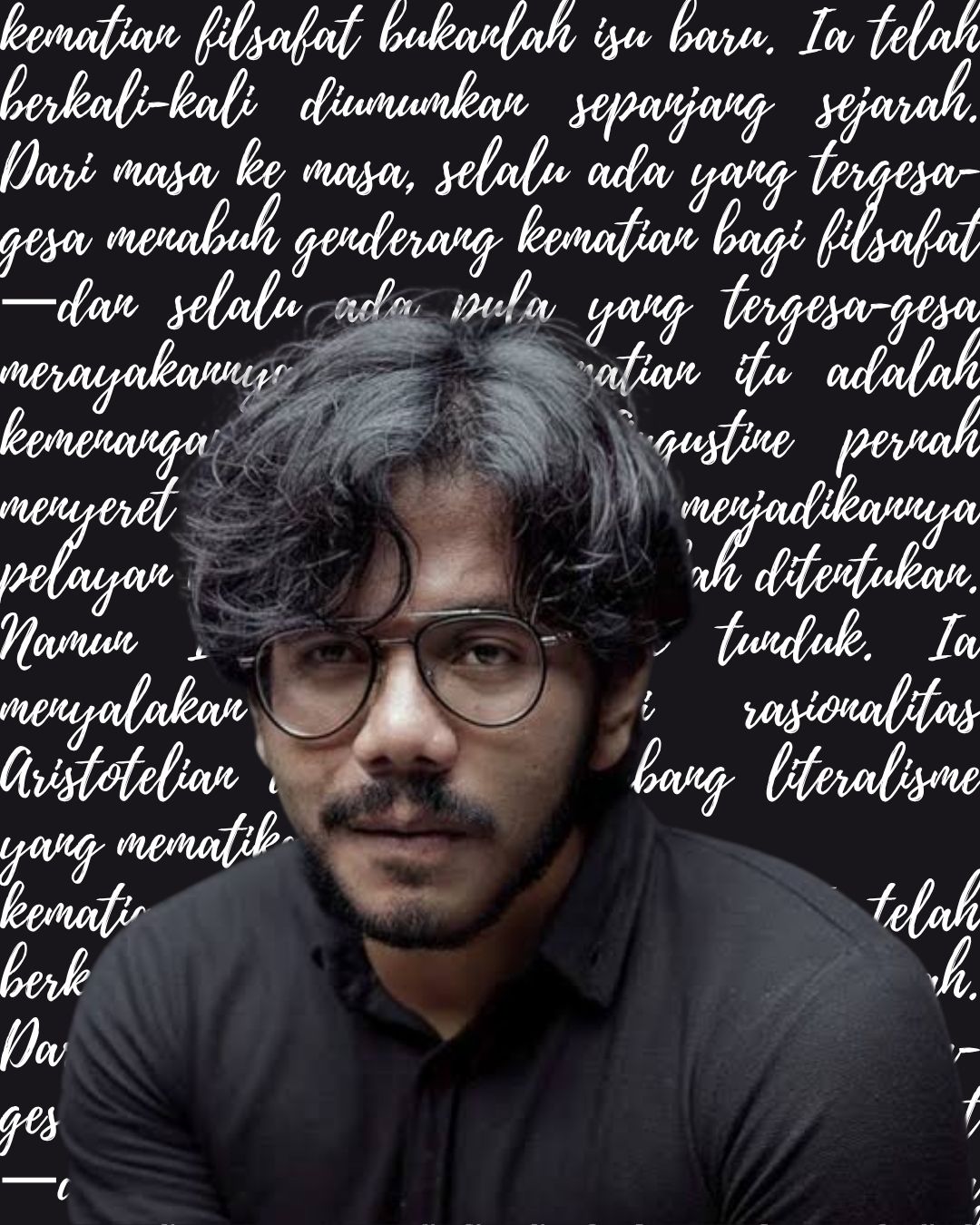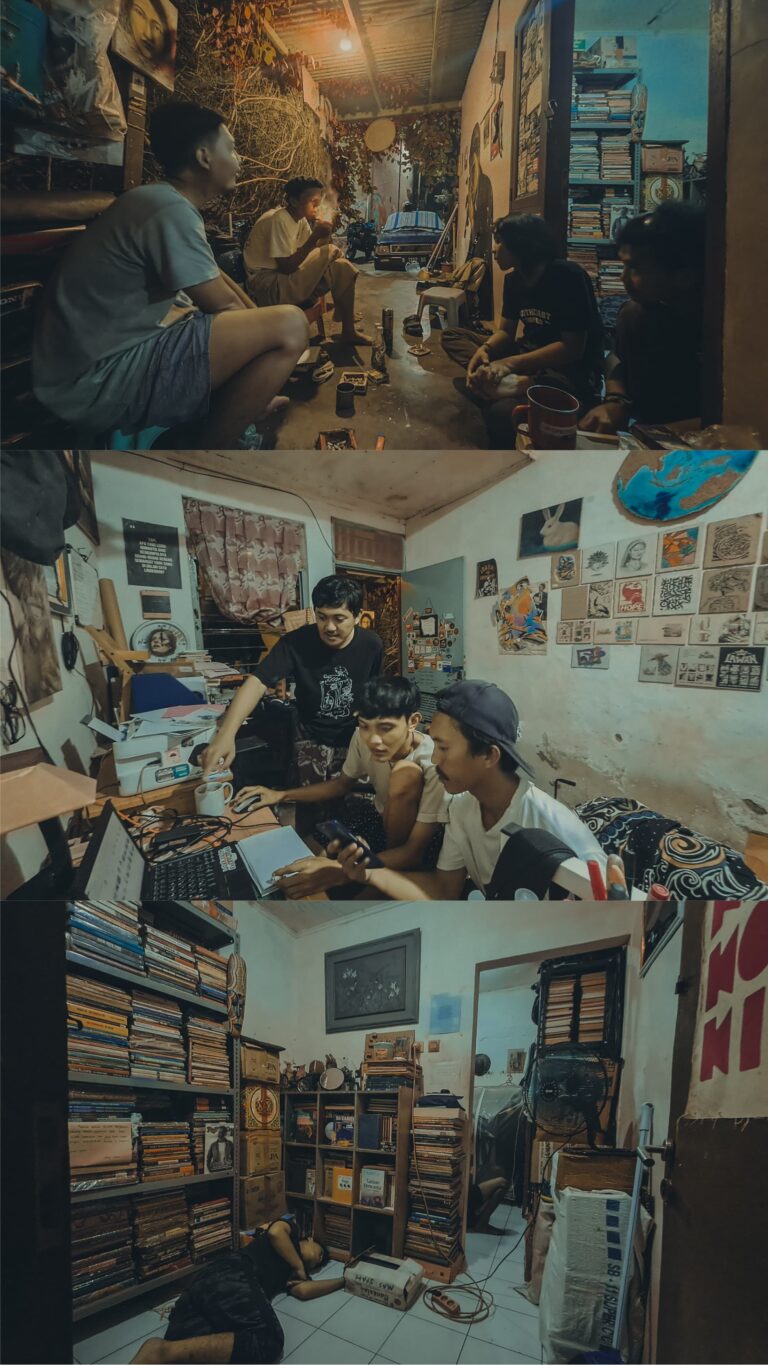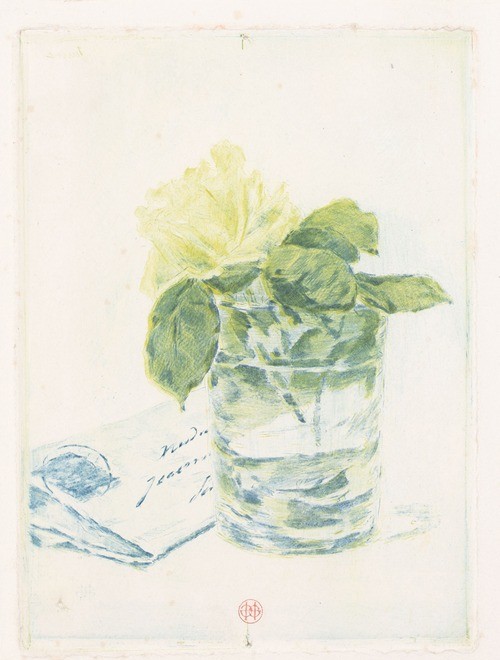Konon, setiap zaman melahirkan nabi-nabinya sendiri. Di negeri ini, seorang nabi datang tak diundang, membawa sabda yang—entah menggelikan atau menyedihkan—bergaung dengan penuh keyakinan: “Filsafat telah mati, dan jurusan filsafat tak lagi relevan.” Namanya Ferry Irwandi. Tapi sebagian orang lebih suka menyebutnya Nabi Ferry AS—Alaihi Stoik. Tidak mengherankan. Sebab hanya dengan jenis kepercayaan yang menyerupai iman religiuslah, kita bisa mengamini pernyataan yang, secara ironis, justru menihilkan aktivitas berpikir itu sendiri.
Dan seperti semua nabi yang datang dengan kharisma yang dikonstruksi, ia tidak datang sendirian. Ia membawa umat. Militan. Kompak. Sigap bersorak, gesit membela junjungan dengan jargon rasionalitas—meski sayangnya, tak selalu disertai cukup rasio. Mereka menyambut sabda edgy itu dengan gegap gempita.
Namun sabda sang nabi bukanlah wahyu baru. Ia hanya gema yang tertinggal dari zaman lain, dari benua yang berbeda. Dalam buku The Grand Design (2010), Hawking sudah lebih dini menyatakan: “Philosophy is dead.” Menurut Hawking, filsafat gagal mengikuti perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Ia tertinggal di belakang, terjebak dalam labirin bahasa dan spekulasi. Tapi satu pertanyaan sederhana menggugurkan pernyataan itu: bagaimana mungkin kita menyatakan bahwa filsafat telah mati, jika pernyataan itu sendiri adalah produk dari perenungan filosofis?
Di sinilah ironi pertama muncul: filsafat dinyatakan mati oleh orang-orang yang tanpa sadar menggunakan instrumen filsafat untuk memproklamasikan kematiannya. Mereka bicara soal kegagalan epistemologi, soal dominasi sains, soal ketidakefektifan logika kuno dalam menjawab tantangan zaman. Tapi bukankah semua itu adalah bentuk dari berfilsafat itu sendiri?
Sayangnya, ironi itu tak berhenti di sana. Yang lebih menyedihkan dari isi sabda Nabi Ferry adalah bagaimana salah satu “skena filsafat Indonesia” merayakannya. Tepatnya, sebuah acara bertajuk “Merayakan Kematian Filsafat?” yang digagas oleh Lingkar Studi Filsafat Odyssey. Poster acara itu beredar luas—dan menjadi viral di X—sebab satu hal yang mencolok mata dan menyengat akal budi: semua pembicara laki-laki. Tak satu pun perempuan. Maka muncullah kesan ganjil yang sukar diabaikan: mungkin filsafat memang telah mati, tapi patriarki tampaknya masih segar bugar bin sehat walafiat.
Beginilah agaknya cara filsafat dikubur di negeri ini: seperti tahlilan abang-abangan yang lupa mengundang ibu-ibu. Sebuah perayaan yang tak hanya eksklusif, tapi juga ahistoris. Seolah-olah filsafat hanya bisa didiskusikan oleh tubuh-tubuh berjakun—dengan suara yang tak boleh terlalu tinggi, terlalu feminin.
Filsafat, yang selama ini punya stereotip buruk sebab terlalu maskulin, kini malah semakin menemukan justifikasinya—mati dan dimakamkan oleh barisan lelaki juga. Tak ada satu pun suara perempuan, tak ada perspektif queer, tak ada narasi dari mereka yang selama ini menjadi liyan dalam sejarah pemikiran. Diskusi filsafat yang sebijaknya kritis dan terbuka itu justru menjadi miniatur dari kamar intelektual yang tertutup, homogen, dan diam-diam angkuh. Yang secara sepintas lebih mirip arena masturbasi intelektual para abang-abangan.
Yang lebih menyakitkan: para pembicara yang terpampang mukanya itu barangkali pernah membaca The Second Sex karya de Beauvoir. Mereka barangkali mafhum bahwa perempuan, sepanjang sejarah, selalu dijadikan the Other: yang liyan, yang berada di luar pusat, yang dilihat tapi tidak dilibatkan, yang diinterpretasi tapi tak pernah diberi ruang untuk menginterpretasi. Maka jika mereka tetap menggelar panggung tanpa perempuan, sesungguhnya mereka sedang menggemakan ulang ketololan Aristoteles: yang menganggap perempuan tak mempunyai logos.
Ini bukan sekadar potret ketidakhadiran perempuan dalam diskusi. Ini adalah bentuk konkret dari penghapusan epistemik—penghilangan sistematis atas kemungkinan berpikir dari tubuh-tubuh yang tak sesuai norma dominan. Di ruang-ruang semacam itu, perempuan bukan hanya tak diberi tempat bicara; ia bahkan tak dianggap perlu hadir.
Sementara itu, di sisi lain, kita tahu: kematian filsafat bukanlah isu baru. Ia telah berkali-kali diumumkan sepanjang sejarah. Dari masa ke masa, selalu ada yang tergesa-gesa menabuh genderang kematian bagi filsafat—dan selalu ada pula yang tergesa-gesa merayakannya, seolah kematian itu adalah kemenangan akal sehat. Augustine pernah menyeret filsafat ke altar iman, menjadikannya pelayan bagi kebenaran yang telah ditentukan. Namun Ibn Rusyd menolak tunduk. Ia menyalakan kembali api rasionalitas Aristotelian di tengah gelombang literalisme yang mematikan. Filsafat tidak mati—ia hanya berpindah arena. Dari agora ke masjid, dari debat ke tafsir, dari Yunani ke Andalusia.
Lalu datang René dengan cogito ergo sum—upaya menyelamatkan akal dari kehampaan. Tapi penyelamatan itu melahirkan keterasingan baru: akal terputus dari tubuh, tubuh terputus dari dunia. Filsafat selamat, tapi umpama hantu: gentayangan, tak berakar, berbicara sendiri dalam ruang gema bernama skeptisisme. Ketika Hegel membangun sistem megah tentang Roh Absolut, filsafat kehilangan vitalitasnya. Ia menjadi peta, bukan perjalanan. Maka Nietzsche datang, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai penyair yang meratap. Ia menggubah kematian menjadi puisi. “Tuhan telah mati,” katanya. Dan bersama Tuhan, filsafat kehilangan orientasi moralnya. Tapi Nietzsche bukan peratap yang pasif. Ia menari di atas reruntuhan. Ia menggoda kita untuk membangun ulang makna, bukan dengan kepastian, tapi dengan ironi.
Dan dari semua tragedi kematian filsafat, tentu tak ada yang segetir nasib Hypatia. Filsuf perempuan dari Alexandria, dibunuh secara brutal oleh gerombolan fanatik agama. Dagingnya dikoyak, pikirannya dilenyapkan. Hypatia dibunuh bukan hanya sebab pikirannya terlalu merdeka, tapi sebab tubuhnya perempuan. Ia adalah martir pertama feminisme intelektual. Di tubuhnya, filsafat tidak hanya mati—ia dibinasakan. Dan dalam kematiannya, kita menyaksikan satu hal yang tetap konstan dari masa ke masa: bahwa berpikir adalah ancaman, terutama jika dilakukan oleh tubuh yang tidak berpenis.
Sebab itu, jika filsafat pernah benar-benar mati, maka warta perihal kematiannya datang melalui beberapa hal, misal: ruang berfilsafat yang tidak inklusif; silabus yang menyempitkan pikiran menjadi soal ujian; ruang dosen yang lebih sibuk mengejar Scopus ketimbang menggugat status quo; ruang-ruang di mana ijazah disinonimkan dengan berpikir; dalam pemikiran pragmatis para “nabi” seperti Ferry, yang mengira filsafat tak lebih dari vespa kuno-butut yang tak lagi relevan sebab tidak bisa lagi ngebut.
Pada gilirannya, beberapa dari kita mungkin tertawa. Tapi itu tawa yang pahit. Tawa getir. Sebab mereka tahu, di balik pernyataan tentang ketidakrelevanan filsafat di zaman kiwari, tersembunyi cermin: bahwa kita hidup dalam zaman yang grasah-grusuh—tidak sabar terhadap proses berpikir. Bahwa filsafat dianggap tak relevan sebab tidak menghasilkan uang. Maka ia dianggap usang, lamban, tidak produktif dan—yang paling memalukan—tidak berguna.
Padahal justru dari ketidakproduktifan itulah kekuatan filsafat berasal. Ia tidak tunduk pada kecepatan. Ia tidak peduli pada kebutuhan industri. Ia tidak mengejar efisiensi. Ia hadir untuk mempertanyakan, bukan untuk menyimpulkan. Ia hadir untuk mengganggu, bukan menenangkan. Ia menolak dikomodifikasi. Filsafat adalah suara yang menginterupsi ruang diskusi yang homogen. Ia adalah perempuan yang dihapus dari kanon, queer yang disingkirkan dari ruang kelas, minoritas yang dibungkam oleh statistik.
Dan selama manusia masih berpikir, filsafat akan selalu hidup. Selama masih ada anak muda yang duduk di kamar gelap dan bertanya: “Apa makna hidup ini?”, selama masih ada orang yang menolak menerima realitas begitu saja, selama masih ada sistem yang menindas dan orang-orang yang berani menggugatnya, filsafat akan terus bernapas. Ia mungkin bisa dipenjara, dicibir, dikeluarkan dari kurikulum—tapi tidak bisa dikeluarkan dari jantung mereka yang berani menggugat dan berbicara.
Apalagi hari ini. Di zaman ketika AI bisa menulis esai, mencipta gambar, bahkan menyelesaikan skripsi, justru filsafat menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sebab ketika mesin bisa meniru pikiran, filsafat mengingatkan bahwa berpikir bukan sekadar mengolah data, tapi juga merasakan, menggugat, dan membayangkan yang belum ada. Ketika kapitalisme algoritmik memaksa kita bekerja lebih cepat, lebih banyak, lebih patuh, filsafat menyela: apa arti hidup yang hanya mengejar efisiensi? Apakah keberadaan kita hanya sah sejauh kita bisa mendatangkan keuntungan?
Filsafat adalah gangguan. Dan justru sebab itulah ia dibutuhkan. Ia adalah penyakit bagi sistem yang ingin segalanya stabil dan dapat ditebak. Ia adalah suara anak kecil yang berkata bahwa mengapa ini harus begini atau mengapa itu harus begitu. Ia adalah bisikan dalam benak yang tak mau tunduk pada narasi besar. Filsafat bukan relik masa lalu. Ia adalah cara manusia melawan penyederhanaan hidup. Ia tidak tinggal di menara gading, tapi bersemayam dalam kerisauan. Dalam puisi. Dalam aktivisme. Dalam sunyi sehari-hari.
Jadi, apakah filsafat telah mati?
Mungkin. Tapi jika benar ia mati, maka ia mati seperti para dewa dalam mitologi: hanya untuk lahir kembali dalam wujud lain. Dan jika suatu hari kita melihat seorang perempuan muda berdiri di panggung, mengutip Plato dari perspektif perempuan kulit hitam, menyebut Freud sebagai misoginis-bajingan, dan menolak dikurung dalam epistemologi patriarki—maka percayalah: filsafat belum mati.
Mungkin, jika kita cukup sabar, kita akan menyaksikan lahirnya generasi baru filsuf—mereka yang tidak menganggap filsafat sebagai ilmu-tidak-berguna-yang-tidak-menghasilkan, tetapi sebagai jalan lengang yang membebaskan. Mereka yang tidak hanya mengutip, tapi juga menggugat. Mereka yang menulis bukan hanya untuk mengasah pisau, tapi bertanya dari mana datangnya luka dan bagaimana menyembuhkannya.
Sementara itu, biarkan kita tertawa bersama para pengikut Nabi Ferry—tawa yang getir, barangkali sedikit lega. Tapi biarkan juga tawa itu menyisakan ruang hening. Sebab siapa tahu, justru di tengah pesta kematian yang paling bising itulah, filsafat sedang tersenyum—diam-diam, pelan-pelan—menanti untuk lahir kembali. Bukan sebagai dogma baru, tapi sebagai makhluk yang lebih lentur, lebih inklusif, dan tak lagi sekadar sibuk mempertanyakan dunia, melainkan juga mengubahnya.