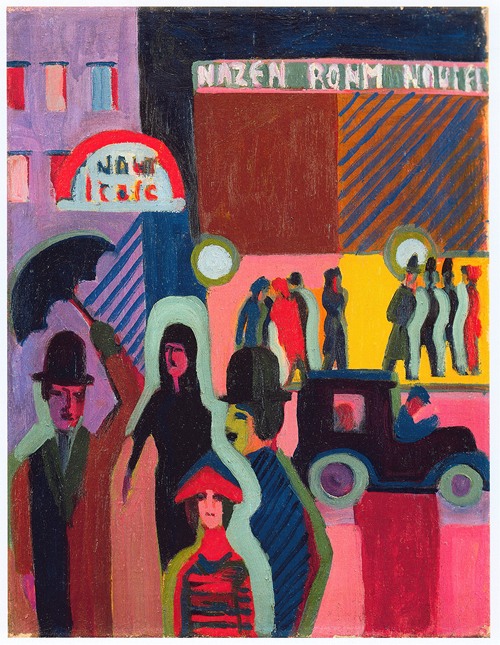“Malam ini saya bergembira. Kegembiraan saya tidak terutama karena rasa senang, melainkan justru karena saya merasa kegelisahan saya meluap-luap. Saya gembira kalau gelisah, dan kegelisahan itulah yang membuat saya merasakan kegembiraan. Kegembiraan ini tak lain karena kita (melingkar di “Semaan Puisi”) bersama-sama untuk menunaikan pembacaan sajak-sajak Frans Nadjira. Salah seorang penyair—yang mengemuka karena kegelisahan dan kecemasan yang membabi buta ini—telah menggembirakan hati saya meski harus menggoreskan luka kembali,” begitu kesan saya usai membacakan sajak-sajak Frans Nadjira pada pertemuan puitik “Semaan Puisi” episode 96.
Semaan Puisi adalah komunitas healing yang memberdayakan puisi sebagai jalan pulang-pergi ke dalam diri dan jeda dari kepenatan duniawi. Semaan Puisi berangkat dari pembacaan sajak-sajak para penyair terdahulu (yang sebagian telah wafat) sebagai upaya kami, sendiri atau bersama-sama, agar sedia berkenalan dengan puisi-puisi serta membaca segenap proses kepenyairannya. Semaan Puisi, barangkali satu-satunya komunitas berpuisi di Depok-Pamulang, yang rutin mengadakan pertemuan tiap kamis seminggu sekali, dan intens dalam menyelami seluk-beluk kegelisahan tiap penyair melalui puisi-puisinya. Demikian kilasan perkenalan singkat yang bisa saya wartakan selaku cantrik yang sedang mengasak diri di “Semaan Puisi”.
Frans Nadjira, satu nama dari sekian banyak nama-nama penyair, yang saya geluti sajak-sajaknya habis-habisan. Sengaja saya pakai kata “gelut” maupun “gulat” tatkala berhadapan dengan sajak. Hubungan saya dengan sajak tidak seakur-semesra laiknya sepasang suami-istri yang saling asyik-masyuk, melainkan seperti rival yang karib yang senantiasa bertarung di alam pembayangan-pengalaman-pembatinan. Inilah kemesraan yang ganjil antara saya dengan/dalam “sajak yang hidup”, seperti kekurang ajaran yang kusukai (sajak “Jendela”). Tak peduli diri walau sebadan-badan seringkali hancur lebur, bahkan babak belur dipukul cemas sajak bertubi-tubi. Untungnya saya pakai jurus Chairil, “aku tetap meradang menerjang”, menyeret langkah duka derita sampai menembusi sajak Frans, “kehidupan, kujelajahi kau, dengan naluri hewaniku” (sajak “Waktu”).
Pertarungan saya dengan puisi di luar sportivitas menang-kalah, karena saya lebih besar dari semua kemenangan dan kekalahan saya atas pemaknaan puisi. Pertarungan ini terjadi karena pergaulan hidup dengan puisi adalah kesempatan untuk merenungi kehidupan. Berarti sekarang waktunya jiwa terpanggil untuk menepi. Karena hanya sunyi yang mengajari kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar ditemukan jawabannya. Hanya sepi yang membimbing kita berdialog dengan apa dan siapa saja, seperti percakapan yang ajaib dalam menjawab kegelisahan eksistensial kita sebagai manusia.
Dan kegelisahan sedemikian akrab, ia hadir dan nyawiji dalam diri Frans. Lewat tempaan hidup bersikap keras pada diri sendiri, Frans kerapkali mengoyak tegangan antara kegelisahan-kegelisahan subtil yang bersifat vertikal dengan horizontal, yang gaib dengan profan, yang ilahiah dengan lahiriah, yang rohani dengan badani, yang gamblang dengan samar, hingga yang terang benderang dengan gelap gulita, dan Frans telah berada pada denyut di antaranya. Dari sini pulalah daya ungkap sajak-sajaknya—yang terbaca dan disarikan untuk kebutuhan Semaan Puisi, terarah pada sesuatu yang jarang kita jelajahi tentang kedalaman. “…sebab kami dalam cahaya, bergetar di udara yang mengalir, muncul dari dalam keheningan, pusat dari tiada, tempat semua bakal kembali, di mana tak lagi menyusup hawa nafsu, yang dihembuskan lewat bilik hati yang lain,” ungkapnya dalam sajak “Hei, Kalian Yang Di Bawah”.
Frans seperti seorang penyelam kontemplatif, ia menyelam ke dasar terdalam kehidupan manusia, dan di kedalaman itu, ia temukan kegelapan: rasa kesiasiaan, ketidakberdayaan, keputusasaan, bahkan penderitaan yang tak perlu disesalkan, karena masih ada harapan, satu titik cahaya di kejauhan. Ia bertukar tangkap dengan menerjemahkan apa yang tak terucapkan, mengungkap rahasia kedalaman yang membutuhkan pemberdayaan kata, menggerakkan fungsi estetis bahasa yang menggugat di dalam segenap pengembaraan-penghayatan batin dan petualangan-pemaknaan rohani.
Dalam sebuah diskusi Semaan Puisi, tiap yang hadir ditagih untuk berani mencoba membicarakan sajak-sajak Frans Nadjira, maka dari itu saya mengajukan pertanyaan atas sajak-sajaknya: “Bagaimanakah caranya menyelam ke kedalaman dasar terdalam hati manusia itu?”
Sementara kita, mungkin hanya saya, cuma ikan kecil di akuarium, sedangkan Frans itu, ikan besar di kedalaman. Saya baru berlatih berenang di kedangkalan, kecetekan, dan di permukaan paling kasar—yang belum sampai paling hening, paling sepi, paling sunyi, paling suwung, dan paling gelap dalam menyelami berlapis-lapis kelembutan hati terdalam manusia. Saya baru menyentuh dasar dari akuarium, Frans sudah menjangkau keheningan yang bersuara. Pandang beringasnya dengan paham /Genggam ganasnya dengan diam: /Jadikan sajak! (sajak “Jadikan Sajak”). Sambil terus ia jelajahi “keasingan yang meresahkan”, istilah Heidegger, lalu menyuarakan begitu banyak tentang apa yang ia dengar melebihi dari apa yang mungkin ia jadikan sajak “Kudengar Desah Pilu Itu” melulur bayang-bayang eksistensial yang mencekam.
“Perlu juga diketahui bahwa”, ujar penyair Mahwi Air Tawar, “Frans itu penyair pertapa. Ia kerapkali juga melakukan puasa Nabi Daud…” Barangkali inilah tirakat panjang yang ia jalani semasa hidupnya. Ditambah pula keteguhan minatnya pada mistisisme, spiritualisme, dan parapsikologi (kegaiban hidup). Dan tak perlu diragukan lagi tangguh tahannya ia dalam menghening, kontemplasi. Hal ini membuatnya tak patah arang dalam menyusuri gelombang pengalaman hidup yang keras dari pengembaraan yang liar, bertemu akrab dengan orang-orang tangguh dalam bertahan hidup, sajak-sajaknya menjadi “cambuk” yang keras, berani, “dan puasa kesabaranku/ kulepas ke angkasa/ menjadi burung gagak/ menjadi mata/ menjadi mulut/ menjadi angin/ menjadi awan/ menjadi halilintar/ menjadi kata yang tak gentar mengucapkan yang benar.” (sajak “Pidato Seorang Mahasiswa di Makam Pahlawan”).
Yang diungkapkan Frans adalah keheningan, dan yang diucapkannya ialah kecemasan. Kecemasan menjadi pintu gerbang keheningan, langkah kecil yang berhati ini telah dipersyarati oleh kegelisahan. Kegelisahan ini meyakinkan dirinya bahwa puisi bisa menjadi wahana keheningan dan sarana kecemasan untuk lepas dari bius dunia dan menyorong pencerahan spiritual. Ia begitu berani dan yakin tangguh tahan pada apa yang sungguh-sungguh sunyi. Di sinilah penciptaan sajak Frans berakar dan bermula dari kepekaan kontemplasinya, yang kemudian mempertajam indranya untuk mengupas seluk beluk eksistensialisme dengan liris.
Meskipun jelas sukar kita menemukan sajak-sajak Frans yang bersuara lirih, lembut, dan membuai. Kalaupun ada, tentu saja sajak tersebut tidak jatuh melenakan, malahan kadang lebih terasa menyentak jiwa, karena aslinya di kedalaman itu, ia menggemakan sajak dengan lantang dan nyaring. Inilah segenap muatan imajis yang pekat dan simbolisme kaya akan kegelapan yang terkandung dalam selubung sajak (yang lirih maupun samar-samar), selubung kata-kata puitik torehan Frans. Berkat diksi-diksinya yang nakal, frasa-frasanya yang segar, metafor-metafornya yang liar itu, sajak-sajak Frans menghadirkan (citraan) penciptaan peristiwa yang kuat dan, sesekali dipadukan dengan lanskap kosmis yang kental. Ini kombinasi kegetiran.
Frans menawarkan puisi yang gagah di tengah kehidupan yang tidak mudah dijalani ini. Lontaran sajaknya sedemikian lugas, tajam, tandas, gamblang, dan penuh letupan metafor yang menggebrak. Meskipun dalam beberapa sajak yang lain, Frans lebih mengutamakan pola mantra yang merepetisi sebagian, atau mengulang bagian tertentu, sehingga mampu memberikan aksentuasi khas pada suasana imajis dan memberi bobot pada nuansa yang liris. Tampaknya ia memang menyukai seruan yang langsung menggertak, tanpa tedeng aling-aling, ia seketika bisa menggugat dengan berteriak lantang, bernada protes tajam, dan menyerukan perlawanan yang nyaring. Barangkali karena sajak-sajak Frans berada pada setiap batas antara yang personal yang sosial, yang kritik yang refleksi, yang suwung yang berisik, maupun yang imajis yang telanjang.
Sebagai pengepul makna, tugas saya ialah memulung segala impresi maupun menggamit segala kesan yang berserakan di dalam sajak-sajak Frans Nadjira, di antaranya melingkari simbolisme gelap yang terselubung, lompatan imaji yang radikal, ketahanan ritme naratifnya, tabir alusinya menggoda, aksentuasinya sarat meresahkan, citraan visualnya membelalakkan mata, efek kejutnya memantik diri, metaforanya yang liar, entakan ritmenya menjerit, dinamika metrum dan matranya terjaga, serta nuansa dan suasananya pekat akan imajis.
Frans dengan sajak-sajaknya itu terkesan kontradiktif. Ia rajin menghening, tetapi sajak-sajaknya seperti menyulut amarah suci. Ia suka merenung, tetapi sajak-sajaknya memercik bahasa protes yang sarat gugatan. Ia rindu kedalaman, tetapi sajak-sajaknya menyiratkan duka derita dari kenyataan kehidupan. Ia gemar kontemplasi, tetapi sajak-sajaknya teramat mempersoalkan segala sesuatu. Ia penyair soliter, tetapi sajak-sajaknya merangkum pedih pilu seorang solider. Ia seperti menanggung amanat penderitaan rakyat yang sebenarnya, tak lain tak bukan, adalah pengalaman lahiriah dan penghayatan batinnya sendiri. Barangkali dengan begini, ia dapat memberdayakan sajak-sajaknya sebagai suatu upaya membangun kembali keutuhan dan keseimbangan manusia.
Sebagaimana pernyataan posisi etisnya Frans sebagai penyair:
“Saya tidak pernah melihat hidup ini cerah. Selalu saya lihat hidup ini dari sisi yang tidak dilihat orang. Saya selalu berdiri di tempat gelap. Dengan satu harapan bahwa dari sisi gelap itulah saya bisa melihat terang di luar. Saya ceritakan sisi gelapnya manusia, sisi pahitnya, sisi sakitnya. Dari situlah saya bisa menyaksikan terang Illahi.”
Ketertarikan saya pada Frans adalah karena kesamaan minatnya pada kegelapan. Saya meyakini adanya terang dalam kegelapan. Buta mata menganugerahi penglihatan. Karena di dalam kegelapan itu, saya belajar membayangkan hal-hal buruk untuk mengharapkan hal-hal baik. Tapi saat ini tak ada kepantasan sedikitpun pada saya untuk mengungkapkan tentang kegelapan. Karena saya mau turuti kata sajak Frans lebih dulu, lebih lama lagi, kian lebih akrab menyelami /dahagaku bermula dari rinduku/ /kepada suara samar kedalaman malam/ /kudengar desah pilu itu/ (sajak “Kudengar Desah Pilu Itu), sebab /kita rindu mendengar suara-suara yang tak terdengar/ (“Sajak Malam Hari”).
30 September 2025