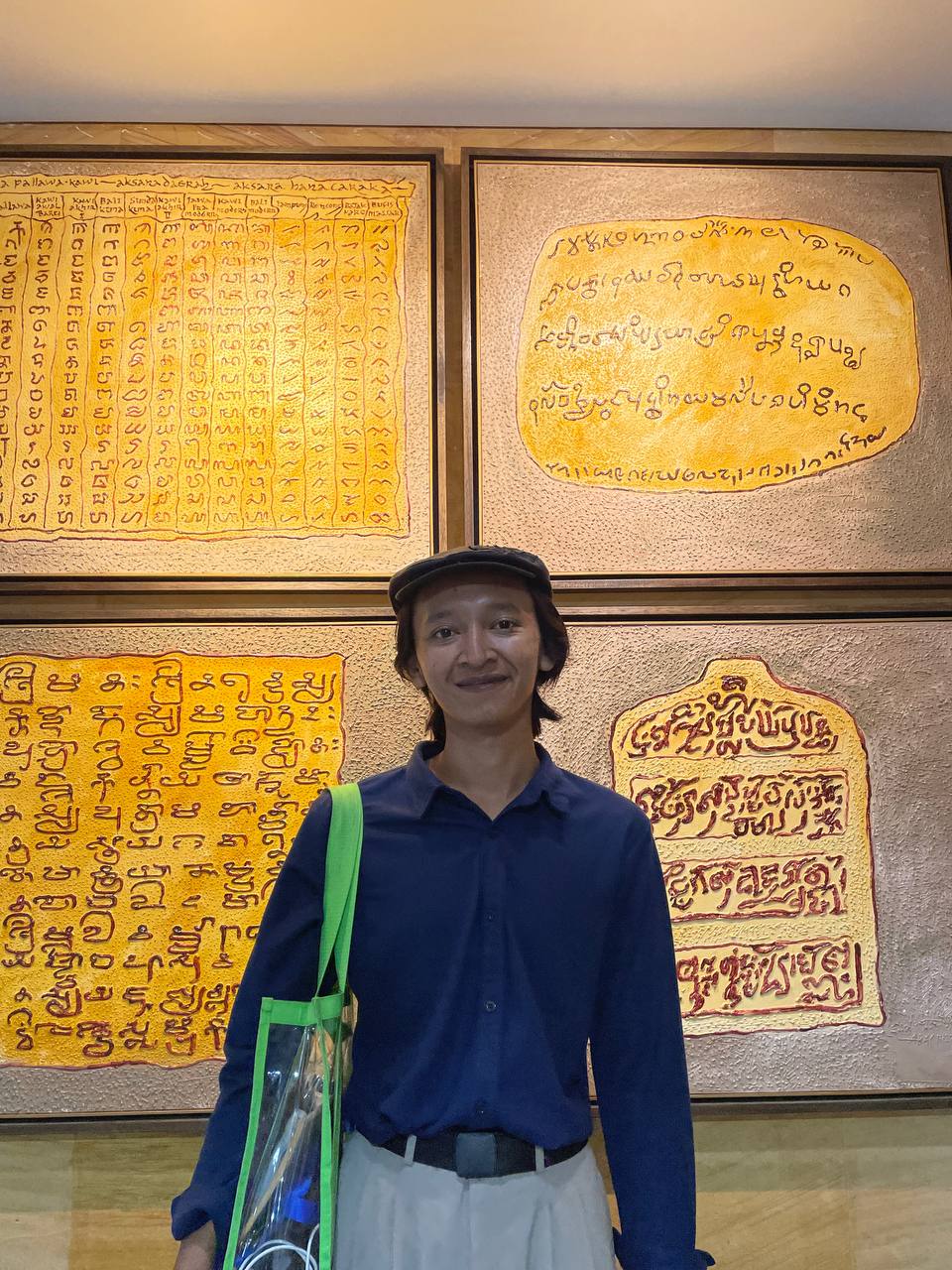Foto: halimunsalaka.com
“…Ahung (semoga selamat). Ini adalah tanda peringatan (kenang-kenangan) Prabu Ratu almarhum, dinobatkan menggunakan nama (gelar) Prabu Guru Dewataprana, dinobatkan (lagi) menggunakan nama (gelar) Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Ya dialah yang membuat parit (pertahanan) Pakuan. Dialah putera Rahiang Dewa Niskala yang dikuburkan di Guna Tiga, cucu Rahiang Niskala Wastu Kancana yang dikuburkan di Nusa Larang. Ya dialah yang membuat tanda peringatan (berupa) gegunungan menancap membuat (hutan) samida, membuat Sanghiang Talaga Rena Mahawijaya. Ya dia-lah, (dibuat) pada tahun Saka 1455.…”
Berbicara tentang Batu-Tulis sebagai nama daerah yang sekarang berada di Kecamatan Bogor Selatan – Kota Bogor, tentu tak bisa lepas dari peninggalan sejarah berupa batu prasasti (Batu-Tulis) peringatan (sakakala) Raja Pajajaran (Prabu Siliwangi) yang terhujam di sana. Sebab, dengan adanya prasasti itulah, hampir seluruh area-kawasan yang dinaungi Kelurahan Batu-Tulis dipercaya oleh masyarakat Bogor sebagai komplek Kerajaan Pajajaran di masa silam, mungkin semacam keratonnya atau bahkan mungkin taman keraton Pajajaran. Dengan demikian, Batu-Tulis sebagai daerah yang berada dalam naungan Kota Bogor menarik untuk ditelusuri masa-silamnya seperti apa, masa kininya bagaimana, dan masa yang akan datangnya akan seperti apa?
Berbahagia dan berbangga-lah orang-orang yang dikaruniai lahir dan besar di daerah seperti Batu-Tulis itu, sebab memiliki nilai-historis peninggalan Kerajaan Pajajaran yang namanya harum seantero-nusantara dan bahkan dunia pada masa kejayaannya. Dan berbahagia dan berbangga-lah pula, orang-orang yang lahir dan besar di Kota yang bernama Bogor ini, terlepas rumitnya persoalan sejarah-budayanya, yang mana kita tahu belum terungkap-terbongkar semuanya, seperti dalam ungkapan lama “pareumen obor” dan “kahieuman bangkong”. Anjay!
Namun bahagia dan bangga saja tak cukup, jika tak dibarengi rasa ingin tahu apa dan mencoba menelusuri bagaimana cerita masa silam itu serta mempelajarinya. Sebab masa silam bukan untuk diagung-agungkan cerita-peradabannya, melainkan dijadikan pembelajaran untuk menempuh masa kini dan masa depan. Lagi-lagi persoalan demikian akan dihadapkan dengan catatan amanat Galunggung, yang berbunyi: ada dahulu – ada sekarang, bila tak ada dahulu – tak akan ada sekarang. Dan sebagainya. Dan seterusnya.
Yang Lampau dari Batu Tulis
Sebagaimana cerita Prasasti Batu-Tulis yang dibuat oleh Prabu Sanghiyang-Surawisesa, pada tahun 1533 Masehi. Pembuatan prasasti tersebut, dilakukan dalam upacara penyempurnaan sukma, untuk mengenang jasa-jasa dan kebesaran ayahnya, Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi). Upacara semacam itu, menariknya hanya dilakukan untuk Raja-raja tertentu (artinya tidak semua Raja Pajajaran dihargai semacam itu). Jika seorang raja wafat, kemudian setelah 12 tahun masyarakat masih menceritakan jasa-jasa dan kebesarannya, maka raja tersebut digali dari kuburnya, kemudian kerangkanya atau diperabukan. Maksudnya, agar sukma Raja tersebut, dapat kembali kepada zat asalnya: Hyang Batara Tunggal (Tuhan Yang Esa).
Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Saleh Danasasmita (dalam Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi, 2015), isi prasasti Batutulis, sebagaimana sudah kita kenali terjemahannya, tidak bertentangan dengan naskah kuna Pustaka Nagara Kretabhumi parwa I sarga 2, yang terjemahan langsungnya, begini:
“Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu: membuat telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibukota Pakuan dan ke hutan larangan. la memperteguh pertahanan ibukota, memberikan desa (perdikan) kepada semua pendeta dan pengikutnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kebinihajian (kaputren), kesatrian (asrama prajurit), pagelaran (macam macam formasi tempur), pamingtonan (tempat pertunjukan kesenian), memperkuat angkatan perang, mengatur pungutan pajak dari raja raja bawahan dan menyusun undang undang kerajaan”.
Setelah upacara penyempurnaan sukma Sri Baduga Maharaja telah dilakukan, masyarakat Kerajaan Sunda (Pakuan Pajajaran khususnya) masih tetap mengenang dan menceritakan jasa-jasa dan kebesaran Sri Baduga Maharaja. Keharuman Sri Baduga Maharaja, oleh masyarakat Bogor dipandang sebanding dengan keharuman nama uyut para pendahulunya, Prabu Maharaja Linggabuana (Prabu Wangi), yang gugur di Palagan Bubat. Juga sebanding dengan keharuman nama kakeknya, Sang Mahapraburesi Niskala Wastu Kancana (Prabu Wangisutah), yang mengangkat Kerajaan Sunda mencapai kejayaannya. Oleh karena itulah, Juru Pantun ataupun Penulis Babad, mengenang Sri Baduga Maharaja sebagai Prabu Silihwangi. Silih artinya pengganti. Wangi artinya harum. Silih Wangi, secara luasnya semacam pengganti Raja-raja termasyhur sebelumnya.
Memasuki cerita penamaan Pakuan Pajajaran untuk Kerajaan Sunda, sesungguhnya terdapat beberapa pendapat, namun yang paling menarik (kemungkinan tepat dan sedikit dekat menemui kebenaran) berasal dari ungkapan Poerbatjaraka (dalam Saleh Danasasmita, 2015), Pakuan Pajajaran merupakan keraton yang berjajar. Jumlah (keraton) bangunan yang berjajar adalah lima, berbentuk panca persada, dan masing-masing diberi nama: Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati (inilah kemungkinan sejarah yang menganggap Batu-Tulis sebagai pusat Kota Pakuan Pajajaran). Dalam pusaran sejarah, nama keraton memang lazim dijadikan nama Ibukota atau nama negara. Contohnya, Saunggalah di Kuningan. Saunggalah (yang berarti, bangunan panjang) sudah tentu merupakan nama keraton, tetapi sekaligus dijadikan nama Ibukota.
Dalam perkembangan selanjutnya, terutama berdasarkan sumber cerita Pantun dan Babad, Kerajaan Sunda lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Pajajaran, sama seperti masyarakat umum yang sepakat menyebutnya Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sedangkan berdasarkan sumber-sumber Portugis, nama resmi kenegaraan, tetap menggunakan sebutan Kerajaan Sunda. Sejalan dengan itu, sebagai anak-cucu (manusia sunda) timbul-lah rasa ingin tahu di dalam diri kita tentunya, mengapa hanya Batu-Tulis yang dijadikan peninggalan Pakuan Pajajaran? Dan mengapa pula di Tatar Sunda tidak banyak ditemukan peninggalan berupa candi, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada?
Pertanyaan demikian akan muncul ketika kita menelisik sejarah kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentunya. Sedangkan jika ketiga daerah itu dibandingkan, bukankah kita tahu, dan sudah terbukti secara artefak-literatur pengaruh Hinduisme justru tersebar pertama-tama di Jawa Barat. Lalu keadaan agama dan hunian geografis antara Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Persoalan itu memang menimbulkan banyak sekali pertentangan pendapat, yang-lalu membuahkan keberagaman versi-cerita. Sebagian berpendapat bahwa batu-batu yang ditemukan di Jawa Barat kurang bagus untuk bahan pembuatan candi. Ada juga yang mengatakan bahwa keyakinan agama orang Jawa Barat agak berbeda meskipun sama-sama terpengaruh oleh Hinduisme. Sedangkan yang paling gegabah menyebutkan bahwa kebudayaan Sunda kuno tertinggal dibandingkan dengan bagian Jawa lainnya. Ada juga yang mengatakan, hal tersebut dikarenakan persoalan politis. Wow! Pendapat mana-kah yang dapat kita pegang-percaya?
Di sini saya hendak menghadirkan sumber yang telah Saleh Danasasmita tempuh-jalani. Sebab, kita tahu betul, sudah banyak pakar yang mengusung serta menguraikan persoalan tersebut. Penelusuran Saleh (meninjau buku Indonesian So-ciety in Transition) amat sangat menarik, ia menguraikan persoalannya bisa dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia bisa dibagi menjadi tiga tipe utama, yaitu masyarakat sawah, masyarakat ladang (huma), dan masyarakat pesisir. Masyarakat Jawa Barat termasuk dalam tipe masyarakat ladang, sedangkan masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali tergolong masyarakat sawah. Lah, apa hubungannya dengan persoalan candi?
Nah, persoalan demikianlah membawa ke ranah perbedaan bangunan masyarakatnya (antara Jawa dan Sunda) itu akan menghasilkan corak kebudayaan yang juga berbeda, bahkan perkembangan sejarahnya pun boleh jadi berlainan. Hampir dapat dipastikan bahwa masyarakat Pajajaran pada umumnya adalah masyarakat ladang, masyarakat huma. Mengenai hal itu, Saleh merujuk pada dokumen sejarah berupa catatan para pegawai Kompeni dalam dagregister sebagaimana yang dikumpulkan oleh De Haan dalam bukunya Priangan (4 jilid).
Dalam bukunya itu diterangkan jelas sekali (catatan: uraian panjang ini nantinya akan membuka cakrawala kita mengenai pertanyaan di atas), bahwa sistem pertanian sawah di Jawa Barat dirintis dan dimulai oleh van Imhoff. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan (intensifikasi) hasil padi. Di wilayah Bogor, persawahan yang pertama kali dibuka adalah di Cisarua. Dengan begitu, Van Imhoff harus mendatangkan petani-sawah dari Tegal dan Banyumas, karena penduduk (Sunda, Jawa-Barat khususnya) belum punya pengetahuan cukup untuk menggarap sawah. Wilayah Sumedang yang pertama-kali dijadikan area persawahan di daerah Conggeang yang petaninya berasal dari Limbangan. Itulah mengapa di Kota Bogor dijadikan daerah bebas huma oleh Yacob Mossel, pengganti Imhoff (1750).
Aturan yang dikeluarkan Mossel adalah, dalam jarak sepuluh jam jalan kaki dari kota Bogor tidak boleh ada ladang atau huma. Kemudian aturan itu ditambah menjadi tiga belas jam perjalanan kaki dari kota Bogor. Meluasnya persawahan di Jawa Barat baru terjadi pada pertengahan abad ke-18. Tidak mustahil, pertanian sawah dimulai pertama kali oleh koloni Mataram di Karawang yang dikirimkan oleh Sultan Agung dan Amangkurat I. Tetapi yang pasti, baru mulai menyebar dalam abad ke-18 setelah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mewajibkan sistem sawah.
Dengan begitu, bisa kita lihat dan telusuri bersama, istilah-istilah yang digunakan oleh petani Sunda dalam membajak sawah: ngawuluku atau ngagaru, umumnya bukan kata Sunda tapi Jawa, misalnya kalen, mider, luput, arang, damping, dan lain-lain. Konon, ada lelucon yang berkembang di pedesaan Sunda, kerbau hanya mengerti bahasa Jawa karena begitulah amanat Prabu Kunda Lalean. Sesungguhnya itu merupakan refleksi bahwa di Tatar Sunda lebih mengenal huma dibanding sejarah sawah.
Saleh juga menghadirkan dokumen literer dari hasil sastera zaman Pajajaran. Tidak lain, meninjau dalam Carita Parahiyangan yang tidak ada istilah petani (patani), tetapi peladang (pahuma). Legenda mengenai Pancakusika memperlihatkan menonjolnya budaya ladang, sebab saudara-saudara Wretikandayun (Raja kerajaan kecil Kendan di daerah sekitar Negrek, yang kemudian memindahkan kerajaan ke Galuh – Priangan timur dan menurunkan Raja-raja di Tatar Sunda). Profesi manusia sunda bisa dibagi dengan empat kemungkinan, ada yang menjadi peladang (huma), penyadap (aren) dan pemburu (panggerek, pamoro), dan ada juga yang berprofesi pedagang. Dalam kisah yang begitu panjang, Carita Parahiyangan hanya sekali menyebut kata sawah, dan itu pun tidak bisa diartikan sebagaimana sawah zaman sekarang, melainkan dalam arti lain, sebagaimana Saleh menguraikan bermakna tempat mandi Raja atau keluarga istana. Goks!
Lalu pada dokumen tradisi, yang mana hari ini masyarakat Baduy tetap bersikukuh dengan kehidupan ladangnya (ngahuma), dan tidak menggarap sawah. Sedangkan dokumen lisan dalam bahasa Sunda modern kata huma berasal dari bahasa Indonesia lama yang arti harfiahnya rumah. Sebaliknya, kata ladang dalam bahasa Sunda berarti hasil atau imbalan. Dua kenyataan itu menunjukkan bahwa bagi orang Sunda zaman dahulu – mereka bertempat tinggal di tempat mereka bertanam padi, karena kata ngahuma (berhuma) dalam bahasa Sunda hanya dikhususkan untuk menanam padi saja. Alhasil, rumah identik dengan huma serta hasil pertanian yang terpentingnya adalah padi-huma. Kata-kata seperti ladang-kesang (hasil keringat), ngaladangan (meladeni) atau taya-ladangna (tak ada hasilnya), menunjukkan bahwa segala rupa hasil dikaitkan dengan hasil tanam padi di huma. Ada lagi kebiasaan di kampung, di pedesaan dahulu, ketika melarang anaknya bertengkar, mereka berkata, “Euh ulah sok paséa jeung dulur, bisi pajauh huma!” (Jangan bertengkar dengan sesama saudara, nanti kelak berjauhan rumah). Ini adalah peribahasa zaman dahulu, yang maksudnya adalah kalau-kalau nanti berjauhan rumah atau tempat tinggal (semacam berjauhan hati).
Setelah kita menyusuri sumber-data kehidupan masyarakat Sunda di atas, tentu akan memberikan gambaran apa, mengapa, bahkan bagaimana bisa terjadi tak ditemukannya candi di peninggalan Kerajaan Sunda. Ciri-ciri masyarakat ladang (huma) inilah kemungkinan yang mendekati kebenaran, sebab umumnya masyarakat huma hidup berpencaran, disebabkan tempat tinggal (rumah) masing-masing yang terpencar sesuai dengan ladang yang sedang digarapnya. Akibatnya, sifat masyarakat ladang cenderung lebih individual dan lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Berbeda dengan masyarakat sawah yang bekerja hanya sampai siang, masyarakat ladang bekerja hingga sore, hampir seharian penuh. Akibatnya, hubungan dengan tetangga agak renggang dan jarang karena letak rumah yang berjauhan.
Dengan demikian, bukankah dapat dimaklumi jika di dalam masyarakat ladang perkembangan bahasa kurang pesat dan kurang luas sebagaimana di dalam masyarakat sawah yang kehidupannya terikat oleh sawah dan selamanya tinggal di kampung (berkumpul). Pendeknya, hasil kesusasteraan ladang bersifat padat berisi, tak banyak hiasan dan kata tambahan seperti dalam kesusasteraan Jawa atau Sunda termutakhir. Dan-lalu, masyarakat ladang tidak kenal terhadap pemujaan leluhur dalam wujud pemeliharaan makam. Hingga kini di Baduy tidak ada komplek makam, walaupun dalam hubungan dengan kepercayaannya mereka menguburkan mayat sebagaimana di tempat lain. Kuburan baru hanya dicirikan oleh pohon hanjuang (sejenis pohon perdu yang biasa ditanam di makam atau di halaman rumah) hingga hari keempat puluh. Setelah melewati waktu itulah, tanah kuburan yang bersangkutan dianggap tanah biasa kembali.
Itulah mengapa, kehidupan masyarakat ladang tidak mukim-menetap, tetapi berpindah-pindah mengikuti perpindahan ladang garapan yang baru. Walaupun orang Baduy pada zaman sekarang sudah membuat perkampungan, tetapi secara berkala tetap harus memindahkan kampung meskipun tidak harus jauh dari lokasi awal, atau katakanlah selalu memindahkan penghuninya jika sudah melewati batas aturan. Dengan kata lain, di Baduy sendiri tidak ada kampung yang tetap di satu tempat, selalu terjadi kemungkinan berpindah (sebagaimana Baduy Dalam). Kembali ke pertanyaan awal, terbuka-kah cakrawala kita terkait mengapa Kerajaan-kerajaan Sunda tidak meninggalkan bangunan megah, seperti candi di Jawa Tengah dan Timur?
Sejauh penelusuran itulah, penelitian Saleh merujuk pada satu hal yang pasti, bahwa candi, seperti yang tampak dalam perkembangan sejarah Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak sesuai dengan pola pikir masyarakat ladang, atau Sunda khususnya (Tentu, hal ini kemungkinan baru dan bukan kebenaran mutlak). Candi merupakan hasil budaya masyarakat sawah. Sebagai contoh, ketika candi Cangkuang (berlokasi di Leles, Garut) mulai digali, hampir seluruh penjuru Pasundan heboh, malah ada yang mengatakan bahwa sejarah kuno Sunda akan berubah hingga ke akar-akarnya. Namun pada akhirnya, entah mengapa seperti menemukan jalan buntu, karena yang ditemukan hanyalah semacam miniatur-candi. Walaupun umurnya memang dapat dirunut ke masa Raja Sanjaya abad ke-8, tetapi tetap saja tak diketemukan candi megah sebagaimana di Jawa. Dan masih banyak contoh tersebut jika kita telusuri bersama.
Para peneliti selalu saja dihadapkan dengan jalan buntu, apabila tetap berpijak dan berdasar pada pendapat usang – yakni mengukur sejarah Sunda lama dengan bahan-bahan sejarah Jawa Tengah maupun Timur. Padahal kenyataannya sosial-budaya-masyarakatnya memiliki tatanan dan bangunan yang berbeda. Saleh juga menekankan, persoalan kasus candi Cangkuang itu sangat logis. Hinduisme mulai meresap di Jawa Barat, mengakibatkan wajar apabila di Jawa Barat ihwal candi juga dicoba untuk dicangkok. Hanya saja karena tidak cocok dengan pola budaya yang ada, maka cangkokan tidak berkembang dengan baik. Dan di Jawa Tengahlah candi bisa tumbuh dengan baik, yang diawali dengan pembangunan candi di kompleks Dieng. Carita Parahiyangan pun hanya menyinggung soal tempat penguburan atau mangkatnya Raja-raja Pajajaran, namun tidak menunjukkan adanya candi di situ.
Walaupun demikian, tentu masalah candi juga ada dalam pikiran masyarakat Pajajaran, sebab pada Koropak 639 juga disinggung perihal candi. Hanya dalam praktek hal itu tidak dipakai (setidaknya tidak populer). Apabila kita berpijak pada sistem-aturan masyarakat huma (sebagaimana uraian di atas), agaknya angan-angan untuk menemukan peninggalan candi yang utuh dan lengkap sebagaimana di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah saatnya ditinggalkan. Saleh menegaskan dengan lugas bahwa, itulah letak kekeliruan para sarjana Belanda dalam mendalami sejarah Sunda kuno.
Lebih gampang lagi apabila kita meneliti prasasti yang ada. Prasasti-prasasti Sunda kebanyakan bersifat langsung dan lugas, tidak berbumbu-bumbu dan tidak menggunakan mantera yang panjang. Dikaitkan dengan ciri tersebut, kita bisa memastikan bahwa Prasasti Jayabupati di Cibadak, bagaimanapun juga bukan hasil kesusasteraan Sunda kuno, baik bahasanya Kawi maupun caranya lebih panjang rajah-mantera daripada yang sama, yaitu padat berisi atau pendek kata panjang maksud isinya. Semua hasil sastera Pajajaran mengandung ciri umum yang sama. Tadi sudah disinggung, titik-tumpu-sumbernya adalah hasil kesusastraan masyarakat huma. Begitu-pula, sakakala (tanda peringat- Sri Baduga) bagi Raja-raja yang termasyur seperti Wastu Kencana dan Sri Baduga, tidak diwujudkan dalam bentuk fisik candi namun cukup dengan prasasti.
Sampai di sini, terbukalah cakrawala kita mengenai peninggalan Kerajaan Pajajaran (Kerajaan Sunda umumnya) tak semegah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan itulah mengapa Batu-Tulis (yang sekarang berada di daerah kelurahan Batu Tulis) tidak menggambarkan wujud-nuansa kemegahan bekas Kerajaan Pakuan Pajajaran. Hal tersebut sejalan dengan uraian di atas terkait persoalan manusia ladang-huma yang selalu berpindah-pindah, bukankah sangat logis? Daripada kita mendengar atau membaca pendapat bahwa tidak adanya reruntuhan Kerajaan Pajajaran disebabkan hancur-lebur oleh Kesultanan Banten, yang sangat-amat kurang meyakinkan. Atau daripada mendengar-membaca pendapat (para siliwangi-isme) bahwa Kerajaan Pajajaran menghilang atau sengaja dihilangkan wujud peninggalannya, yang sangat-amat tak masuk dalam pemikiran modern kita. Heuheu!
Yang Kini dan Yang Akan Datang dari Batu Tulis
Batu Tulis sebagai daerah, nama Kelurahan Batu-Tulis khususnya, tentulah berakar dan berasal dari banyaknya situs-situs atau prasasti peninggalan Kerajaan Pajajaran yang berbentuk Batu dan kebanyakan bertuliskan huruf jawa kuno (Palawa). Sehingga nama Batu-Tulis dijadikan nama Wilayah atau Kelurahan di Kota Bogor, tepatnya di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Dengan demikian, bagaimana bekas hunian Pakuan Pajajaran atau salah-satu lokasi Keraton Pakuan Pajajaran sedemikian sederhana dan malah tidak meninggalkan jejak megah apa-apa, selain batu peringatan, situs punden-berundak, dan penerkaan geografis yang mendukung (sebagai lokasi Kerajaan) menyangkut kebenaran logisnya.
Suatu daerah tentunya akan mengalami perubahan serta pembangunan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat setempat dalam menghadapi perjalanan hidup. Batu-Tulis sebagai daerah sama saja seperti daerah hunian Bogor lainnya, Kota ataupun Kabupatennya, sama-sama sudah berubah mengikuti alur peradabannya. Namun yang menarik, di daerah Batu Tulis, khususnya di sekitaran Prasasti Batu-Tulis dewasa ini, sedang dibangun Museum Sri Baduga atau Museum Pakuan Pajajaran. Walau terkesan sangat amat terlambat, tentu hal tersebut layak kita apresiasi dan kita dukung bersama sebagai bentuk usaha merawat peninggalan Nenek-moyang (khusunya Pakuan Pajajaran).
Penataan kawasan Batu Tulis memang sudah lama direncanakan pemerintah Kota Bogor, dan mulai ramai dibincangkan serta mulai dimatangkan pada tahun 2020, dengan menggelar sarasehan bersama akademisi, warga, komunitas hingga budayawan di Balaikota Bogor. Tentu hal tersebut sangat amat terlambat, jika kita bandingkan dengan Kota Bandung yang sudah mempunyai Museum Sri Baduga, yang didirikan sejak tahun 1974 dengan memanfaatkan bangunan lama bekas Kawedanan Tegallega, yang-lalu kemudian diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Daoed Joesoef.
Kemudian ditetapkan melalui Kepmendikbud nomor 02223/0/1990 tanggal 4 April 1990. Nama Museum Sri Baduga diambil dari nama seorang raja Padjajaran yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji yang sempat memerintah pada tahun 1482-1521 Masehi. Bahkan koleksi Museum Sri Baduga (di Bandung), memiliki ribuan koleksi benda-benda bersejerah, mulai dari arkeologi, geologi, biologi, histori, etnografi, teknologi, filologi, keramonologi, seni rupa, numismatika dan heraldika. Lalu, apakah yang hendak Pemerintah Kota Bogor pamerkan di Museum Sri Baduga atau Museum Pakuan Pajajaran di Batu-Tulis? Mengapa Pemerintah Bogor seperti kalah cepat mengurus peninggalan sejarah-budaya daripada Pemerintah Bandung? Apakah Sri Baduga Maharaja di mata Pemerintah Bogor tidak penting, padahal ia bertahta di Pakuan Pajajaran (Bogor hari ini), tapi malah Bandung yang lebih dahulu? Heihee, ganjil sekaligus aneh!
Berita tersebut sudah tersebar luas di media Bogor khususnya, tentang prosesi membangun museum di kawasan Batu-Tulis, Seperti laman-media Universitas Pakuan mengungkapkan bahwa Wali Kota Bogor, Bima Arya, melakukan sarasehan agar mendengar masukan dari sudut pandang yang beragam, termasuk sudut pandang akademis, sejarawan, budayawan, dan dari masyarakat umum tentang perencanaan penataan kawasan Batu Tulis. Bima Arya juga memperlihatkan desain awal yang akan didiskusikan dengan budayawan dan masyarakat umum. Rencana tersebut mencakup area parkir, pusat informasi, kegiatan seni, ruang publik, diorama kerajaan, dan elemen lainnya. Kemungkinan akan ada dua lantai dalam perencanaan tersebut.
Hal tersebut tentu layak diapresiasi kembali, yang mana Pemerintah Bogor sampai sejauh ini berarti sangat acuh untuk mengembangkan persoalan kesenian dan kebudayaan serta kawasan bersejarah, yang menyimpan peninggalan dari salah satu kerajaan terbesar di Nusantara: salah-satunya Pakuan Pajajaran. Sementara di sarasehan itu, Profesor Nina Herlina Lubis, Guru Besar Ilmu Sejarah dari Universitas Padjadjaran, memberikan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Bogor dalam usaha membenahi kawasan Batu Tulis. Ia juga memberikan masukan dengan mengusulkan konsep “living concert” atau pertunjukan hidup yang disertai dengan Museum Kerajaan.
Bahkan Prof Nina menekankan bahwa penataan ini tidak perlu mengganggu infrastruktur yang ada saat ini, melainkan lebih kepada melestarikan peninggalan sejarah yang tersebar di daerah tersebut dan menghidupkannya dengan cara yang sesuai dengan zaman sekarang. Lebih lanjutnya, Ia mengharapkan kepada Pemerintah Kota Bogor agar dapat menciptakan konsep eko-museum, seperti yang ada di Roma, Italia. Ini sangat menarik, sebuah konsep mengintegrasikan peninggalan sejarah ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengganggu masyarakat, menjadikan kawasan tersebut semacam museum yang hidup.
Nah, sekali lagi, walaupun terkesan lambat, ini layak kita tunggu, akan seperti apa dan bagaimana daerah Batu-Tulis nanti beserta Prasasti Batu-Tulis dan peninggalan sejarah lainnya. Oleh sebab, dengan pembangunan museum semacam itu, atau katakanlah membikin pusat kesenian-kebudayaan-kesejarahan dalam satu titik, amat sangat membantu kita sebagai anak-cucunya yang hendak menelusuri pijakan apa dan bagaimana sejarah hidup Nenek-moyang kita sendiri. Ditambah, jika Pemerintah mampu membuat semacam miniatur Kerator Pakuan Pajajaran (bersumber pada peneliti sejarah sebagai titik-tolak desain), mungkin akan sangat-amat-menarik, dan hal itu akan menyirami rasa haus kita bersama terhadap bagaimana sebenarnya wujud Kerajaan Pakuan Pajajaran.
Jika kita terus merunut uraian di atas sebelumnya, maka jelaslah masa yang akan datang dari wujud Batu Tulis sebagai daerah, bisa kita bayangkan semacam pusat kesenian-kebudayaan-kesejarah sebelum terciptanya Bogor, khususnya pertalian hidup Bogor dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pembangunan museum itu sangat penting untuk pelestarian warisan sejarah Kerajaan Pajajaran. Selain untuk melestarikan dan merawat artefak-artefak sejarah tersebut. Kita bisa menjadikan Museum Pakuan Pajajaran menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat setempat dan wisatawan umumnya tentang sejarah, budaya, dan peradaban Kerajaan Pajajaran, sebelum Bogor tercipta. Ini tentu membantu meningkatkan kesadaran sejarah di kalangan masyarakat dan menjalari nilai edukasi kepada generasi muda tentang akar budaya mereka sendiri.
Museum itu pula bisa menjadi pusat penelitian yang penting bagi calon para sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan sosial yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kerajaan Pajajaran, Bogor khususnya. Ini memungkinkan mereka untuk menggali lebih dalam pengetahuan tentang masa lalu atau katakanlah wisata sejarah. Dalam kerja-kerja wisata, pemberdayaan manusia setempat dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi lokal, baik melalui sektor pariwisata, dan sebagainya. Sekaligus dalam kerja-kerja seni-budaya, Museum dapat memberikan wadah untuk mempamerkan seni dan budaya lokal: seperti seni sastra, seni rupa, seni pertunjukan, kerajinan tangan, musik, dan tradisi lokal lainnya. Dan yang tak kalah penting, museum sebagai wahana yang ideal untuk mengadakan pertunjukan seni, pameran, dan berbagai acara kebudayaan.
Huah! Persoalan demikian tentu akan menghasilkan dampak yang banyak sekali, terkhusus nilai pembelajaran bersama, dengan catatan: Pemerintah Kota Bogor mestilah serius dalam membangun dan mewujudkan dampak positif ketika melestarikan nilai kesenian-kebudayaan-kesejarahan, sebagaimana sudah saya uraikan di atas. Sisanya, kita tunggu saja, benarkah wujud Batu-Tulis nanti akan seperti catatan ini, atau malah sebaliknya, sebagaimana museum-suntuk menyekat-nyekat kehidupan seni-budaya di dalamnya, dan lebih parah desain kaku dan koleksi yang sangat minim mengakibatkan sepi tanpa pengunjung. Semoga saja tidak demikian. Semoga, ya.
–
Kepustakaan:
Melacak sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi (2015), Saleh Danasasmita.
Sejarah Bogor (1983), Saleh Danasasmita.
Sundakala (2005), Ayatrohaedi.
Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian (naskah kuno tahun 1518 Masehi, “1981”), oleh Atja dan Saleh Danasasmita.